 Oleh Zely Ariane [1]
Oleh Zely Ariane [1]
13 tahun lalu Soeharto memang harus ditumbangkan. Keputusan tersebut adalah langkah brilian dari satu generasi….”
[Nurul Khawari, pelaku penggulingan Soeharto-Orde Baru Mei 1998, Solo Pos, 5 Mei 2011]
Demokrasi adalah ibu kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, kebudayaan dan semua bentuk kreativitasnya, yang bermanfaat bagi masa depan kemanusiaan. Bukan untuk demokrasi rakyat jatuhkan Soeharto di tahun 1998, melainkan untuk keadilan dan kesejahteraan. Bukan untuk reformasi mahasiswa dan rakyat menduduki gedung MPR, melainkan untuk Indonesia yang bebas dari todongan senjata dan mata-mata tentara, bersih dari korupsi dan nepotisme, sejahtera karena bahan-bahan pokok dapat terjangkau. Demokrasi adalah alatnya; demokrasi adalah caranya, untuk mencapai tujuan pembebasan manusia dari penindasan manusia lainnya. Tanpa demokrasi, kemanusiaan menjadi hitam-putih tak berwarna, kesejahteraan menjadi komoditas milik penguasa.
Gerakan reformasi mahasiswa dan rakyat telah berhasil menjatuhkan diktator, memperluas partisipasi politik rakyat langsung lewat sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan yang terpenting, telah berhasil mengembalikan senjata politik rakyat yang paling ampuh yaitu aksi massa. Namun, gerakan tersebut belum sanggup menjatuhkan sebuah rezim kapitalis militeristik dan menggantikannya dengan yang lebih demokratik dan kerakyatan. Gerakan tersebut juga gagal berkonsolidasi lebih lanjut dan mendorong demokrasi lebih maju lagi. Gerakan kalah di dalam dua pertarungan besar: kalah melawan tentara-militerisme dan Golkar serta kalah melawan hegemoni kekuatan anti demokrasi.
Demokrasi kini dikanalisasi ke dalam insitutusi-institusi yang secara sepihak dinyatakan sebagai perwakilan kehendak rakyat, dipersulit oleh birokrasi dan permainan uang, dikunci oleh kepentingan pemodal, status quo dan kontrol senjata serta penjara. Sejak saat itulah demokrasi bukan lagi wujud kehendak rakyat, melainkan kehendak segelintir elit untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaannya.
Ketika aksi massa mengubah aturan main
Demokrasi, ketika ia berada langsung di tangan rakyat; ditentukan langsung oleh rakyat; tak satupun perangkat hukum dalam masyarakat kapitalisme dapat berkata tidak: buktinya, Soeharto dapat dipaksa mundur.
Dari semua elemen demokrasi universal, yang berhasil dimenangkan pada reformasi 1998 di Indonesia, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul-berorganisasi-berpartai, kebebasan informasi, pemilihan umum yang langsung dan jurdil, terdapat satu elemen utama yang paling fundamental, yaitu aksi massa. Aksi massa menuntut dan terorganisir adalah kunci perubahan politik tahun 1998. Pengamat Indonesia yang menerjemahkan Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer, Max Lane, mengatakan dalam bukunya Indonesia Bangsa yang Belum Selesai, bahwa secara politik, kediktatoran Soeharto telah dijatuhkan sesaat ketika politik mobilisasi rakyat; politik aksi massa mulai digunakan kembali sebagai senjata perjuangan melawan politik massa mengambang Orde Baru di pertengahan tahun 90-an.
Orang dapat berspekulasi bahwa kejatuhan Soeharto adalah hasil dari intervensi AS yang memandangnya tak lagi sebagai agen yang efektif dan efisien bagi kapitalisme internasional. Jikapun teori konspirasi itu benar—tokh tidak haram hal tersebut dilakukan AS—tanpa pergolakan massa yang sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an, Soeharto tak akan dianggap tak efisien dan tak efektif oleh AS. Sehingga pergolakan massa tetaplah faktor utama perubahan—terlepas siapapun dan apapun yang membonceng perubahan itu di kemudian hari.
Aksi massa sangat penting bagi sejarah politik di Indonesia karena ia memegang peran kunci dalam menghantarkan Indonesia merdeka sekaligus menjadi ciri politik utama Indonesia sebelum 1965. Dan politik inilah yang paling pertama dihancurkan oleh Orde Baru setelah 1965 sampai ke akar-akarnya: dipenjarai dan dibunuhi aktivis-aktivisnya, dilabeli propaganda hitam perspektif yang mendukungnya. Aksi massa telah menjadi hantu selama tahun-tahun berkuasanya Orde Baru, dan berbalik menjadi malaikat di masa-masa awal reformasi, dan menjadi kambing hitam belakangan ini.
Organisasi-organisasi barupun bertumbuhan, sementara yang lama didesak mereorganisasi diri ataupun melahirkan perpecahan. Hasil yang paling kentara dari proses ini adalah pertumbuhan dan perpecahan serikat-serikat buruh dan partai politik. Berdirinya beragam komite dan kelompok-kelompok mahasiswa, dibandingkan tahun-tahun sebelum reformasi, jumlahnya meningkat pesat. Semua organisasi baru tersebut mengusung jargon-jargon reformasi, bahkan organisasi lama status quopun dipaksa untuk tunduk dalam bendera reformasi.
Tetapi kebebasan informasi, pemilu langsung, sistem multipartai, otonomi daerah, yang merupakan beberapa hasil reformasi 1998 mulai dijadikan kambing hitam sumber persoalan, serta inefisiensi, oleh kekuatan status quo. Bukan salah reformasi jika keadaan demokrasi saat ini memburuk; bukan berarti Orde Baru lebih baik jika Orde Reformasi seakan-akan tampak lebih carut marut. Reformasi 1998 justru telah mengubah aturan main, menciptakankan berbagai macam ruang untuk prakondisi demokrasi yang lebih maju dan esensial. Di sisi lain ia juga memberi landasan perubahan secara fundamental prinsip-prinsip kelembagaan negara.
Namun demikian, landasan tersebut menjadi tak bermakna jika tak ada kekuatan politik demokratik dan progresif yang menggunakan dan mengolah manfaat darinya. Seperti landasan udara yang tak akan ada fungsinya tanpa pesawat udara yang mendaratinya. Selain itu, reformasi pun memiliki batas dalam dirinya sendiri. Ia hanya mengubah apa yang ada di permukaan, bukan mengubah yang ada di kedalaman. Ia hanya mengganti genteng bocor, bukan mengubah kerangka atap. Reformasi tak bisa mengubah sistem yang berurat akar pada penindasan manusia atas manusia. Reformasi tak bisa membuat kapitalisme dan militerisme melayani kemanusiaan.
Langkah-langkah mundur
Sedikit demi sedikit beberapa keberhasilan paling penting dari perjuangan demokrasi 1998 diambil kembali dari tangan rakyat, padahal agenda dan sebagian tujuannya masih jauh dari tercapai. Rakyat masih dapat berdemonstrasi namun aturannya semakin diketatkan—misalnya sekarang demonstrasi dalam jumlah besar saja yang terpaksa dibolehkan parkir di seberang Istana Merdeka di Jakarta padahal sebelumnya bisa beberapa meter dari gerbang Istana. Aturan-aturan berorganisasi dan berpartai yang semakin dipersulit, termasuk pemberangusan serikat buruh, adalah diantara contoh-contoh menyakitkan.
Baru-baru ini jagad aktivisme dikejutkan oleh survey indobarometer bahwa 40,9% rakyat menganggap kondisi di bawah pemerintahan Orde Baru-Soeharto lebih baik ketimbang masa reformasi. Terlepas dari metodologi dan kredibilitas survey tersebut, saat ini memang wacana pihak kanan/status quo/konservatif lah yang mendominasi penilaian terhadap reformasi . Pertama, masa Orde Baru baru lebih baik ketimbang sekarang; kedua, demokrasi saat ini sudah kebablasan, tidak efisien, dan boros. Sementara satu kesimpulan dari kelompok gerakan sosial progresif yaitu reformasi gagal menghantarkan rakyat untuk mencapai kesejahteraan—bahkan kehidupan rakyat semakin memburuk. Ketiga pandangan tersebut sama-sama mengandung satu pengertian—walau berbeda landasan—yaitu: reformasi saat ini gagal.
Bagi kaum sosial progresif, atau yang mengaku kaum kiri revolusioner, terdapat tiga kegagalan utama reformasi yang paling penting, sekaligus membedakannya dari kepentingan kaum status quo dalam melihat reformasi. Reformasi ini tidak berhasil mengubah watak militeristik, kedudukan dan fungsi fundamental tentara melalui berbagai komando teritorialnya—walau berhasil menghalau tentara dari parlemen. Reformasi tak berhasil mengadili jenderal-jenderal pelanggar HAM berat termasuk diktator Soeharto. Reformasi tak berhasil melemahkan kekuatan partai penopang utama Orde Baru, Golkar dan kroni Soeharto. Ketiga hal ini merupakan elemen politik fundamental yang menjadi ukuran kegagalan perjuangan demokrasi di Indonesia.
Tidak benar masa Orde Baru lebih baik ketimbang sekarang. Orde Baru dengan kekuatan penopang utamanya, Golkar dan Tentara, justru penyebab historis kemiskinan sistemik Indonesia saat ini dengan terlebih dahulu melakukan pembantaian dan pemenjaraan jutaan rakyat tak berdosa yang dituduh komunis karena menjadi penghambat pengembangan ekonomi kapitalistik Orde Baru. Merekalah para kapitalis raksasa Indonesia yang selanjutnya menggadaikan rakyat dan kekayaan alam Indonesia di kaki penjajahan modal internasional melalui UU Penanaman Modal tahun 1967.
Sejak saat itu, Indonesia yang sebelumnya sedang mencoba bangkit mengatur ekonomi dan politik-budayanya sendiri lepas dari dominasi imperialisme, semakin menjadi ladang subur penghisapan. Buruh murah, kekayaan alam diobral sehingga lingkungan hancur tak bermasa depan, rakyat dililit hutang luar negeri—bahkan sejak lahirpun per kepala bayi sudah menanggung hutang negara dan swasta jutaan rupiah—industri hanya untuk melayani pasar internasional tak dibolehkan berkembang lebih terencana untuk kebutuhan rakyat dan pasar domestik, keragaman kebudayaan rakyat dikebiri dengan penyeragaman budaya Indonesia yang dipaksakan dengan senjata. Budaya Indonesia yang dahulu dinamis menjadi statis, keragaman hanya diwujudkan melalui beragam kesenian dan pakaian daerah, bukan keragaman pikiran, ekspresi dan tindakan politik. Rakyat tak boleh berpolitik, bekerja dan berkarya saja sesuai kehendak pemerintah demi pembangunan ala dan untuk Soeharto serta kroninya di bawah todongan senjata tentara. Karena itulah Widji Tukul menggambarkan Indonesia layaknya berselimut kedamaian palsu.
Banyak pendapat awam mengatakan hidup di masa Orba lebih enak karena harga barang-barang pokok dianggap lebih murah dibanding sekarang. Itu terjadi karena rata-rata upah yang didapat saat itu masih relatif menjangkau harga bahan pokok. Dan itu juga terjadi bukan karena Soeharto-Orde Baru berpihak atau baik pada rakyat, namun, salah satunya, karena ekonomi kapitalis dunia saat itu masih mentoleransi pemberian subsidi rakyat, sementara saat ini mereka tak lagi mengijinkannya. Oleh karena itu upah riil saat ini semakin tak sanggup membeli bahan-bahan pokok karena kenaikan harga (subsidinya sudah dikebiri) tak sesuai dengan kenaikan upah.
Pendapat status quo lainnya juga menyatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini kebablasan. Jusuf Kalla menyatakannya sebagai demokrasi yang mahal—karena terlalu banyak pemilihan langsung dan jumlah partai politik. Dan yang lebih jahat adalah pendapat pengamat Intelijen, Wawan Purwanto, yang mengatakan bahwa: “lambannya penanganan teroris di Indonesia lebih disebabkan karena munculnya reformasi. Tidak semudah pada saat zaman dahulu ketika orde baru masih berkuasa… Dulu masih ada Undang-undang subversif mudah menanganinya…” (7/5/2011).
Pendapat terakhir mencerminkan watak khas ideologi Orde Baru yang militeristik, tidak bisa memahami, tidak membutuhkan dan memusuhi demokrasi. Dan ideologi ini masih banyak penganutnya, apalagi dikalangan birokrasi. Pernyataan Jusuf Kalla juga mencerminkan posisi pragmatis dan anti demokrasi karena tidak bisa melihat pentingnya partisipasi rakyat dan dinamisasi politik di dalam pemilihan umum langsung dan pendirian partai politik. Pemilu tahun 1955 juga terdiri dari banyak partai, namun kehidupan politik berlangsung begitu dinamis dan partisipasi politik rakyat serta perbedaan pandangan politik berlangsung terbuka begitu nyata. Itulah pendidikan politik yang sebenarnya buat rakyat.
Hersri Setiawan, seorang penyair dan aktivis Lekra, mengomentari reformasi 1998 sebagai gelombang besar yang berhasil membuat rezim militer Suharto tumbang, tetapi tidak turut atau belum menumbangkan militerisme , karena “isme” adalah sebuah konsep kebudayaan. Pernyataan Hersri benar di dalam konteks bahwa militerisme memang masih menjadi momok di negeri ini. Penambahan komando teritorial tentara, keterlibatan militer dalam konflik pertanahan serta penembakan kaum tani, keterlibatan petinggi militer dalam pembentukan mayoritas partai-partai politik peserta pemilu, wacana bahwa pimpinan politik yang berlatar belakang tentara lebih baik dari sipil, wacana nasionalisme sempit dalam perdebatan batas-batas wilayah, dll, adalah diantara wujud-wujud pikiran dan tindakan militeristik yang masih terus terjadi.
Reformasi memang tak bisa berhasil menuntaskan ini semua tanpa gerakan sosial progresif yang hidup, terarah dan terus menerus mendesakkan tuntutannya. Gerakan sosial progresif gagal menunjukkan ideologi alternatif melawan kapitalisme, melawan ideologi birokratisme dan militerisme khas Orde Baru, melawan konservatisme-fundamentalisme reaksioner yang mendapat tempat di tengah kekosongan ideologi alternatif. Inilah sumber penyebab kekalahan utama perjuangan reformasi di Indonesia.
Gerakan tidak sanggup memanfaatkan kesempatan dan potensi mengubah aturan main politik, pada fase-fase awal reformasi, dengan baik. Kemungkinan sebab ketidaksanggupan tersebut adalah pada kenyataan bahwa gerakan masih berumur sangat muda dengan teori-teori strategi dan taktik perjuangan yang belum kaya dalam menghadapi perubahan situasi politik. Namun penyebab ini harus diurai dengan lebih bertanggung jawab pada materi lain karena membutuhkan penilaian dan pemeriksaan seksama terhadap problem-problem gerakan sosial progresif dan kiri di Indonesia pasca reformasi.
Di sisi lain kekuatan penguasa borjuasi jauh lebih cepat berkonsolidasi dibandingkan gerakan pasca reformasi 1998. Penjatuhan Gusdur tahun 2001 adalah tonggak paling pertama bersekutunya borjuasi reformis pendukung reformasi 1998 dengan sisa Orba dan tentara, sehingga kaum reformis tersebut segera tampak jelas karakter gadungannya. Kaum reformasi gadungan tersebut (PDIP dan PAN yang paling kentara diantara yang lainnya) terbukti sama-sama tak punya karakter, tak punya prinsip, dan pengecut: segera berkhianat dan mendukung kekuatan sisa orde baru. Sejak saat itu serangan balik borjuasipun mendapatkan kekuatannya.
Setelah berhasil melakukan konsolidasi politik dengan menjatuhkan Gusdur, konsolidasi ekonomi kapitalisme masif dilakukan di era pemerintahan Megawati. Ciri utama ekonomi kapitalis internasional pasca Soeharto adalah menggalakkan neoliberalisme dengan menghancurkan sebagian besar perlindungan negara terhadap pasar. Seluruh kebutuhan dasar rakyat seperti bahan-bahan pokok, perumahan, pendidikan dan kesehatan harus dikomersialisasi.
Pemerintahan Megawati-PDIP lah yang paling berperan besar dalam menjatuhkan Indonesia lebih dalam ke jurang ketergantungan terhadap imperialisme melalui kebijakan privatisasi perusahaan yang menyangkut hajat hidup rakyat, penandatanganan berbagai surat kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang membuat Indonesia semakin terjerat dalam mekanisme keuangan kapitalis internasional. Pemerintahan SBY pun melanjutkan skema ekonomi kapitalistik yang serupa dengan perbedaan tekanan kebijakan dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, misalnya, SBY lebih banyak mendulang hutang luar negeri ketimbang pemerintah sebelumnya, membuka keran liberalisasi lebih deras lagi. Semua tujuan ekonomi politik mereka sama: sama-sama menjadi anak baik imperialisme, sama-sama tidak punya visi jangka panjang peningkatan kesejahteraan rakyat.
Serangan-demi serangan terhadap hak ekonomi dan sosial politik rakyat pun harus terus dilanjutkan demi stabilisasi ekonomi dan politik borjuasi pasca reformasi. Kekalahan gerakan buruh yang masif melawan revisi UU Ketenagakerjaan tahun 2003 adalah titik balik perjuangan buruh di Indonesia sekaligus surga bagi fleksibilitas tenaga kerja yang dibutuhkan neoliberalisme di Indonesia. Sementara stabilisasi politik mulai menemukan bentuknya dan terarah sejak pemilu 2004. Sejak saat itu pula hampir tak ada bedanya kekuatan pro reformasi dengan kekuatan sisa orde baru, apalagi ketika tokoh-tokoh aktivis-aktivis mahasiswa pelaku reformasi 1998 berduyun-duyun masuk menjadi pendukung dan kandidat partai-partai pengkhianat reformasi dan pro orde baru tersebut. Pemilu 2009 melanjutkan konsolidasi serupa dan mengerucutkan kekuasaan borjuasi pada beberapa partai politik utama saja.
Tidak cukup disitu, konsolidasi politik borjuasi diperamai lagi dengan kemunculan organisasi dan partai seperti Nasional Demokrat dan Nasional Republik yang keduanya membawa nuansa kembali ke orde baru atau restorasi. Sumber-sumber kekuatan politik baru ini masih saja Golkar dan tentara. Bahkan yang terakhir dipimpin langsung oleh anak Soeharto: Tommi Soeharto.
Persoalan mendesak saat ini
Saat ini ditengah persoalan pelik dia tas, kita dihadapkan lagi pada ancaman besar masa depan perjuangan demokrasi. Rancangan UU Intelejen dan KUHP adalah dua proyek besar status quo untuk mengembalikan ciri militeristik dan anti demokrasi dalam politik Indonesia. Kedua RUU ini akan disahkan bulan Juli mendatang. Pendapat pengamat intelejen di atas menyangkut dibutuhkannya kembali semacam UU anti subversif sebagai legitimasi penangkapan warga sipil mewakili alasan dipersiapkannya rancangan UU semacam itu.
Fenomena meningkatnya terorisme, dan gerakan Negara Islam Indonesia terlepas siapapun dalang, tujuan dan kepentingan di belakangnya, dimanfaatkan negara untuk menakut-nakuti rakyat sekaligus meningkatkan represi dan pengawasan aktivitas sosial politik rakyat melalui RUU ini. Dua RUU ini menjadi semacam pelengkap dan penyimpul bagi berbagai serangan hak-hak demokrasi rakyat yang meningkat di masa pemerintahan SBY-Boediono ini.
Di dalam rilis Koalisi Advokasi RUU Intelejen, terlihat ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi rakyat di dalam RUU tersebut, terutama dalam pasal-pasal terkait rahasia informasi intelejen, penangkapan sewenang-wenang atas nama kerahasiaan, dan ketiadaan mekanisme kontrol rakyat dalam bentuk apapun atas nama kerahasiaan negara.
Sementara di dalam salah satu pasal RUU KUHAP dinyatakan dengan jelas bahwa “barangsiapa secara melawan hukum menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk, dan perwujudannya” dan “setiap orang yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme- dapat dipidana”.
Ancaman lainnya adalah fenomena meningkatnya tindakan-tindakan sepihak anti keberagaman, konservatisme dan fundamentalisme reaksioner. Penyebab meningkatnya fenomena ini tidak dapat diurai lebih dalam di sini karena membutuhkan pemeriksaan dan penilaian lebih mendalam diartikel yang lain. Namun seperti dinyatakan sebelumnya, bahwa reformasi 98 memberikan landasan keterbukaan bagi semua kepentingan untuk berkonsolidasi dan berkontestasi meraih dukungan rakyat. Dalam pertarungan ini, gagasan konservatisme yang justru mampu maju ke depan, sementara gagasan progresif, gagasan sosialis, gagal menunjukkan dirinya.
Semua ini harus kita hadapi di saat yang bersamaan. Sebagaimana sulitnya, hambatan-hambatan dan serangan-serangan ini harus dilawan.
Untuk satu langkah maju
Di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia saat ini, jalan keluar sekecil apapun tetap berada di pundak kaum pergerakan sosial progresif yang (seharusnya) memiliki iman demorkasi yang tangguh, di tengah kenyataan historis tak ada satupun kekuatan elit yang memiliki iman demokrasi yang sungguh-sungguh. Tak ada jalan lain bagi kaum sosial progresif selain berkonsolidasi untuk membendung serangan-serangan terhadap demokrasi sambil terus melanjutkan perjuangan untuk keadilan ekonomi.
Perjalanan reformasi sudah memberikan pelajaran berharga bahwa reformasi itu sendiri sudah tak cukup lagi. Sekarang semakin terbukti, untuk perjuangan reformasi sekecil apapun membutuhkan mobilisasi rakyat, membutuhkan revolusi politik untuk mereorganisasi sistem kekuasaan, ekonomi, dan kemasyarakatan secara radikal.
Persoalannya saat ini adalah konsolidasi gerakan sosial progresif dan gerakan kiri tak banyak mengalami kemajuan. Pergerakan untuk hak-hak ekonomi sering terpisah dan sulit disatukan dengan perjuangan politik dan demokrasi. Padahal hak ekonomi tidak dapat dipenuhi dan kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa demokrasi. Ketiadaan alat politik alternatif yang cukup dominan dan berperan memberi penyadaran terhadap akar dari problem-problem rakyat, juga menyulitkan penyatuan tersebut.
Jalan keluarnya mesti dirumuskan bersama karena persoalan ini pun harus diatasi bersama. Pendapat Gramsci menyangkut konsolidasi persatuan sangat tepat untuk memberi inspirasi kemandegan koonsolidasi gerakan saat ini: “kita harus mengembangkan kesatuan, kesadaran dan kedewasaan gerakan, membuatnya menjadi kekuatan yang kuat dan kohesif, dan kemudian dengan sabar, dengan perhatian seksama terhadap kondisi kontekstual, menanti momen yang menguntungkan untuk menggunakan kekuatan ini”.
Demikian pula terhadap tanggung jawab gerakan dalam berposisi terhadap problem-problem politik di lapangan praktis, Gramsci melanjutkan: “bila kekuatan yang segaris ini hendak memiliki pengaruh historis yang penting, mereka harus langgeng dan secara organik/menyatu berhubungan dengan kondisi-kondisi di lapangan, bukan sekedar konvergensi sesaat. Untuk mengembangkan momentum massa, mereka harus mendemonstrasikan, baik dalam imajinasi rakyat maupun dalam aksi, bahwa mereka mampu meraih kekuasaan dan melaksanakan tugas-tugas yang mereka tetapkan sendiri.”
Kepentingan gerakan sosialisme terhadap demokrasi
Sekarang kita tiba pada pertanyaan mengapa kita, gerakan untuk sosialisme, gerakan sosial progresif, gerakan demokratik, sangat berkepentingan terhadap demokrasi? Dan mengapa kita tidak bisa berharap dan tidak bisa percaya bahwa kapitalisme pro demokrasi?
Itu karena demokrasi dan kapitalisme tidak akan sejalan, karena kapitalisme tidak membutuhkan konsep dasar demokrasi yang paling utama: partisipasi langsung mayoritas rakyat. Kapitalisme tidak berkeberatan dengan para diktator dan kediktatoran selagi mereka berkesesuaian dengan kepentingan akumulasi keuntungannya. Di dalam Negara dan Revolusi Bab 5, Lenin menyatakan, “dalam masyarakat kapitalis kita memiliki demokrasi yang dikebiri, menyedihkan, palsu, suatu demokrasi untuk kaum kaya, yang minoritas”.
Demokrasi dalam kapitalisme adalah demokrasi untuk para pemodal yang posisi dan ekonominya bebas dari kontrol rakyat. Cukup rakyat diberikan dewan-dewan perwakilan tanpa rakyat diberi hak memecat para wakil yang dipilihnya sendiri; cukup rakyat diberikan institusi-institusi ‘demokratis’ sebagai fungsi perwakilan atas aspirasinya tanpa perlu mengerti dan terlibat langsung. Semuanya bertujuan satu: menjauhkan rakyat dari politik, karena politik yang mereka kehendaki adalah politik yang melayani kepentingan pemodal, bukan politik rakyat. Demokrasi seperti ini akan membuat masyarakat apatis, dekaden, pasif tak punya kekuatan politik dan dimobilisasi hanya untuk kepentingan kelas penguasa.
Batasan-batasan demokrasi di dalam kapitalisme dapat kita lihat dengan sangat jelas, misalnya ketika negara kapitalis berhadapan dengan radikalisasi tuntutan-tuntutan demokrasi dan kesejahteraan. Negara kapitalis tak segan-segan mengambil tindakan kekerasan dan represi, tak lagi memperdulikan prinsip-prinsip demokrasi yang diklaimnya sebagai fondasi. Di saat itulah niat sejati demokrasi dalam kapitalisme akan terbongkar.
Sebaliknya, perjuangan untuk sosialisme adalah perjuangan membalik semua logika demokrasi terbatas kapitalisme tersebut. Sosialisme menghendaki perluasan partisipasi politik rakyat, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus berkuasa atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, mengutip pernyataan Aung San Syu kyi pada pembukaan ASEAN People Forum di Jakarta 3-5 May 2011, bahwa demokrasi akan serupa penampakan saja tanpa elemen-elemen fundamentalnya. Elemen fundamental tersebut, dari contoh Revolusi Perancis yang merupakan perjuangan demokrasi (revolusi demokratik) paling akbar, meliputi: kedaulatan rakyat, hak azasi manusia, kekuasaan konstituen, kewarganegaraan, pengawasan rakyat, dll. Semua ini memang lahir sebagai kepentingan borjuasi di awal-awal revolusi, namun dalam perjalannya demokrasi akan membahayakan mereka, sehingga rakyat pekerja lah yang paling berkepentingan mempertahankan bahkan meluaskannya—itulah makna penuntasan revolusi demokratik.
Perjuangan sosialisme membutuhkan perluasan logika demokrasi ke wilayah-wilayah politik yang lebih luas, termasuk memerangi birokratisasi negara—yang merupakan satu bentuk depolitisasi massa. Perjuangan sosialisme bahkan mempolitisasi dan mendemorkatisasi seluruh bidang kehidupan rakyat: ekonomi (melalui perjuangan kelas), bahkan rumah tangga (melalui perjuangan feminisme).
Sosialisme sangat berkepentingan terhadap demokrasi, karena sosialisme hanya dapat terwujud dengan demokrasi. Sosialisme membutuhkan sumbangan pikiran, tindakan (partisipasi) seluruh rakyat secara langsung untuk membicarakan dan mencari jalan keluar atas problem-problem kehidupannya. Semakin banyak yang terlibat, semakin kaya dan berhasil sosialisme. Itulah sebabnya perjuangan sosialisme harus terus menerus mengintervensi perjuangan politik dengan serius karena setiap langkah kemajuan atau kemunduran politik akan berpengaruh pada kemungkinan kemenangan sosialisme itu sendiri.
Politik dicirikan oleh konflik, keputusan, kekuasaan dan situasi-situasi yang tak dapat diperkirakan dengan matematis, yang kesemua itu menjadi landasan dalam penentuan taktik-taktik perjuangan untuk sosialisme. Oleh karena itu, kaum sosialis harus mengambil peran sebesar-besarnya di dalam perjuangan demokrasi. Karena perjuangan demokrasi hanya akan menguntungkan kita, bukan kekuatan-kekuatan status quo dan pro kapitalisme. Perjuangan demokrasi untuk sosialisme adalah pembuka jalan atas perubahan sistem yang berurat akar pada penindasan manusia atas manusia.***
[1] Anggota KPRM-PRD; aktivis Perempuan Mahardhika.



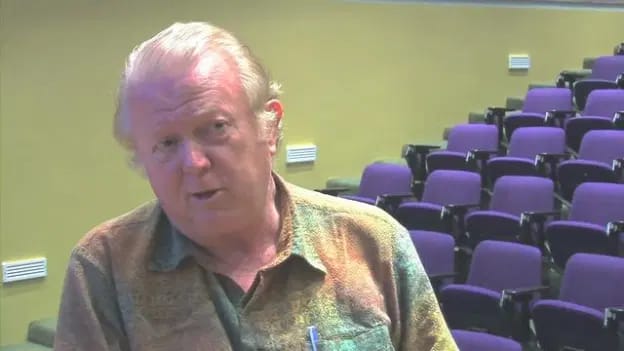
Nice writing 😉
Tetapi saya ada pertanyaan, mungkin bisa diskusi.
Bagaimana menjawab pertanyaan bahwa kadang apa yang disebut sebagai demokrasi adalah kekuasaan atas suara mayoritas? Apa itu juga sebagai bentuk hitam putih model baru?
Dari istilah saja demokrasi memang kuasa mayoritas (rakyat), tetapi bukan tirani mayoritas. Maksud Krisna “bentuk hitam putih model baru” bagaimana ya? Trims komentarnya.