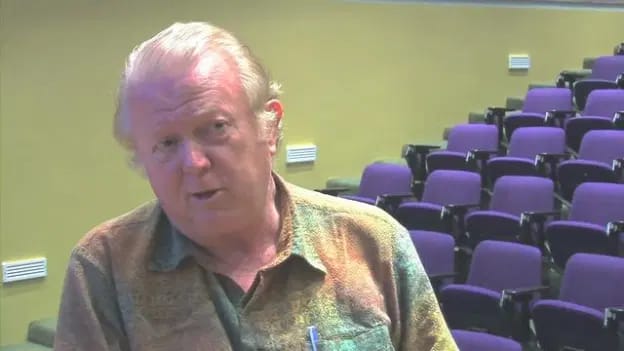Pemilu Elit 2009, baru saja rampung, dengan meninggalkan “segunung” persoalan administratif dan substansial demokrasi prosedural yang lebih banyak menguntungkan kaum elit. Tapi, yang pasti, pemilu elit 2009 sudah berhasil merekonsolidasikan kekuatan elit-elit politik yang semuanya menguntungkan korporasi internasional, sehingga membuat arah kebijakan ekonomi-politik ke depannya tidak akan berubah secara fundamental, kecuali ada faktor yang radikal dan revolusioner—yang tentunya berasal dan gerakan dan rakyat.
Persoalan pemilu elit 2009 tidak saja berkisar dalam soal daftar pemilih ganda atau banyaknya warga yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya, tetapi ada persoalan mendasar lainnya, yakni: politisasi dan partisipasi semu. Secara umum partai-partai yang terlibat dalam pemilu 2009 tidak memberikan pendidikan politik yang kongkret kepada rakyat maupun anggotanya. Kampanye-kampanye yang dilakukan tanpa makna, tanpa program yang kongkret, yang dapat memberikan harapan nyata bagi persoalan mendesak rakyat: demokrasi dan kesejahteraan. Apa yang dilakukan kaum elit dalam pemilu 2009 dengan iklan, spanduk, poster, dan alat-alat peraga kampanye lainnya, hanyalah bagian dari hegemoni untuk mengkondisikan rakyat bergerak ke tempat-tempat pemungutan suara, tanpa partisipasi ataupun kesadaran politik—mengerti konsekuensi apa yang diperbuatnya. Partisipasi rakyat, hanya ada di bilik-bilik suara, sedangkan dalam proses sebelumnya, rakyat hanya sekedar obyek propaganda, tak ada program yang diusulkan langsung oleh rakyat. Kemudian, hasil dari pemilu tak pernah bisa dirubah atau dikontrol oleh rakyat karena demokrasi untuk rakyat hanya pada pemilu saja, selebihnya, demokrasi diantara elit-elit itu sendiri.
Tingkat ketidakpercayaan terhadap elit semakin tinggi!
Hal yang positif yang tidak akan pernah dinilai sebagai aspek kemajuan oleh kelompok gerakan yang terkooptasi (pro pemilu), adalah adanya ketidakpercayaan terhadap elit-elit politik yang prosentasenya masih cukup besar. Jika dilihat dari perbandingan golput pada Pemilu tahun 2004—sebesar 22.9% dari jumlah pemilih 147,216,531—pada tahun 2009 prosentase golput untuk pemilu legislatif meningkat menjadi 39,21% dari jumlah pemilih sebanyak 121,588,366 (dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 171,265,442). Kemudian, dalam pemilu presiden 2009, prosentase golput sebesar 27,88% dari jumlah pemilih sebanyak 127,983,655 (dengan jumlah DPT sebesar 176,411,434 ditambah dengan keputusan MK yang memperbolehkan untuk ikut memilih hanya dengan KTP dan Paspor, sehingga ada pertambahan jumlah daftar pemilih yang cukup besar). Dari DPT KPU saja, terdapat penambahan sekitar 49, 677,076 pemilih. Kalau pemilu legislatif 2009 diperbandingkan dengan pemilu presiden 2009, ada penurunan prosentase golput 11,33% atau sekitar 18,839,194. Jumlah golput pada pemilu presiden (27,88%) bisa saja secara pragmatis dianggap menurun apabila kita menutup mata pada kenyataan besarnya kecurangan pemilu melalui daftar pemilih ganda. Tercatat, dari beberapa gugatan, diindikasikan DPT ganda berkisar 7–25 Juta suara. Apabila diambil margin terendah maka prosentase golput kurang lebih 31%. Tanpa penambahan prosentase golput dari persoalan DPT ganda, sesungguhnya tingkat golput pada pemilu 2009 sudah tinggi, pada tahun 2004 saja prosentase golput sebesar 22.9%.
Dari perbandingan prosentase golput pada pemilu 2004 dengan 2009, tak dapat dipungkiri lagi, ada penurunan tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit, yang coba dinafikkan oleh kelompok-kelompok parlementaris. Bahkan, meski sudah diilusi dengan janji-janji semu dan propaganda sok populis (seperti yang dilakukan oleh PDIP, HANURA, GERINDRA, dan lainnya), grafik golput justru tidak menurun tapi justru malah meningkat (dari pemilu 2004 ke pemilu 2009). Peningkatan golput ini memang tidak serta-merta menjadi suatu kekuatan politik, tapi harus dinilai positif sebagai perubahan kesadaran rakyat: dari percaya menjadi tidak percaya pada elit-elit politik; dan yang semakin meyakini bahwa persoalan-persoalan kongkret yang mereka hadapi sehari-hari tidak akan sanggup dicari jalan keluarnya oleh partai-partai maupun calon presiden dan calon wakil presiden yang ada (sejauh mereka masih menggunakan jalur ekonomi pasar bebas—pen.). Perubahan kesadaran rakyat ini harus dijadikan basis untuk terus didorong maju oleh gerakan agar bermuara pada keyakinan untuk mempercayai kekuatannya sendiri, meyakini metode politiknya sendiri, meyakini sekutu-sekutu perjuangannya, dan meyakini jalan keluarnya, bukan sebaliknya, memundurkan perkembangan maju kesadaran rakyat dengan membenar-benarkan partai-partai borjuasi dan tokoh-tokohnya saat bersekutu bersama mereka atau turut mengkampanyekan salah satu calon presiden-wakil presiden dengan melabelisasi mereka sebagai borjuis progresif; kerakyatan; nasionalis; atau bahkan anti imperialis/neoliberalis, padahal tak ada sama sekali rekam sejarahnya partai-partai borjuis tersebut ataupun capres/cawapres yang ada terlibat dalam mobilisasi rakyat untuk menolak semua dampak-dampak dari kebijakan neoliberalisme, seperti kenaikan BBM, privatisasi kampus, liberalisasi beras, listrik mahal, penggusuran, dll.
Sadar akan kondisi kemiskinan yang menimpa sebagian besar rakyat, dan sadar bahwa neoliberalisme adalah biang keladinya, membuat seluruh partai-partai reformis gadungan dan sisa-sisa orde baru, dengan tanpa malu akan dosa-dosa politik mereka, bicara soal anti neoliberalisme, anti imperialisme dengan “berani”nya. Bahkan menuding satu sama lain di kalangan para elit itu sendiri (seperti yang dilakukan oleh Mega-Pro, JK-Win kepada rival mereka) sebagai agen-agen neoliberalisme. Padahal semuanya sama saja, sama-sama pro neoliberalisme. Sungguh suatu politik bermuka dua (political ambivalent) dari kaum elit tersebut—menyedihkannya, dibenar-benarkan pula oleh beberapa kelompok gerakan yang juga melabelisasikan dirinya, KIRI. Sungguh suatu pembodohan.
Mari kita lihat berbagai program-program kampanye partai-partai borjuis dan calon presiden/wakil presidennya yang semakin kongkret bertujuan menggerakkan rakyat untuk memilih mereka. Berikut program-program mereka:
- Megawati-Prabowo, membuat target pertumbuhan ekonomi dua digit (10%); dengan jaminan empat bulan pertama perekonomian akan stabil. Konsep Ekonomi kerakyatannya, memprioritaskan pertanian, kehutanan, dan sektor strategis lainnya. Mempertahankan kedaulatan negara, melalui ketahanan pangan dan melindungi petani. Menjanjikan adanya kontrak dan peraturan yang betul-betul mengikat bagi investor asing, agar tidak merugikan investor dalam negeri.
- Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono, selama dua tahun ke depan akan berfokus pada pemulihan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada 2014, pertumbuhan ekonomi yang merata di pusat dan daerah, serta tidak bertumpu pada sektor industri saja. Selain itu, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, subsidi ditekan, dan anggaran yang boros akan dipotong.
- Joesoef Kalla-Wiranto, membuat target pertumbuhan ekonomi 8-9% pada 2011, menekan subsidi listrik dan energi, melanjutkan projek pembangkit listrik 10 ribu megawat, konversi BBM (minyak tanah) ke gas, pembangunan infrastruktur besar-besaran, menjaga keamanan dan stabilitas politik, serta mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Disamping fokus program kampanye di atas, Megawati-Prabowo bahkan berani mengilusi rakyat dengan melakukan kontrak politik, diantaranya: kontrak politik mencabut UU BHP, menghapuskan sistem Outsourcing terhadap buruh, menjanjikan kemudahan mendapatkan bahan bakar, kredit usaha dan modernisasi alat tangkap ikan bagi kaum nelayan. Secara umum, dalam konsep kampanye, baik Megawati-Prabowo, SBY-Boediono, maupun JK-Win, berbicara soal menegakkan kedaulatan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin HAM dan demokrasi, mengembalikan martabat bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain. Pendek kata, semua (dalam porsi lebih besar ada pada Mega-Pro dan JK-Win) berbicara soal nasionalisme dan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Rekam Sejarah
“Jangan sekali-sekali melupakan Sejarah!”, ini yang sering diungkapkan oleh Bung Karno. Betapapun sederhananya seruan tersebut, maknanya penting dan tak terbatas ruang dan waktu, terlebih saat ini. Dalam situasi krisis seperti saat ini, kaum borjuis, terlebih yang oportunis, dapat menggunakan segala cara, berbagai topeng untuk mendapatkan simpati rakyat, guna memuluskan jalan menuju kekuasaan politiknya, apakah itu dengan tiba-tiba berposisi anti neoliberalisme, anti imperialisme, sok nasionalis, ataupun tiba-tiba menjadi neososialis. Sungguh murah mengubah pandangan politik, tanpa harus digembleng terlebih dahulu oleh pengalaman panjang berjuang bersama rakyat. Ya, itulah yang dilakukan oleh elit-elit politik negeri ini, politik oportunis—yang dilegitimasi oleh aktivis-aktivis yang juga oportunis.
Agar rakyat tak lupa—dan memang sebagian besar tak lupa—mari kita lihat apa saja (pada prakteknya) yang sudah dilakukan oleh partai-partai borjuis dan calon-calonnya itu:
- Masa Pemerintahan SBY dan Kalla (yang juga incumbent)—Boediono (menjabat sebagai Gubernur BI)—: Tercatat terjadi peningkatan total utang luar negeri secara signifikan dari Rp. 662 triliun (2004) menjadi Rp. 920 triliun (2009); kemudian, posisi utang dan obligasi dari dalam dan luar negeri mencapai Rp 1.695 triliun, meningkat dari Rp 1.275 triliun ketimbang lima tahun lalu; di masa pemerintahan SBY-Kalla, harga BBM naik sebanyak lima kali. dengan kenaikkan BBM maka jumlah orang miskin diperkirakan sekitar 59 juta orang (sangat) miskin; jumlah orang yang termasuk setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terus meningkat, dari 29 juta (2006) menjadi 31 juta (2007). Demikian juga jumlah orang yang bekerja pada kegiatan informal terus naik dari kisaran 60% menuju 70%. Semua ini menunjukkan kualitas hidup pekerja di Indonesia mengalami kemerosotan. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2009 mencapai 8,14 persen atau 9,26 juta orang; dalam soal privatiasi, pemerintahan SBY-Kalla, pada tahun 2007, memasukan 15 BUMN dalam daftar privatisasi. Tahun 2008, jumlah BUMN yang masuk daftar obral oleh pemerintah membengkak menjadi 44—tapi tertunda karena adanya krisis; untuk produk UU, pemerintah mensahkan berbagai UU anti rakyat miskin, antaralain: UU Investasi, UU Pornografi, UU BHP, dll.
- Masa Pemerintahan Megawati—dengan menteri-menteri seperti SBY, Kalla, dan Boediono (menteri keuangan)—: Saat meninggalkan Istana Negara pada tahun 2004, Mega meninggalkan tanggungan utang sebesar Rp 1.275 triliun. Kemudian, menambah sebesar Rp 180 triliun utang luar negeri selama ia berkuasa; 6 bulan pertama memerintah Megawati sudah menjual 7 BUMN, antaralain: Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara. Pada Maret/April 2004, Pemerintahan Megawati mengajukan privatisasi 28 BUMN. BUMN itu terdiri dari 19 BUMN dan 9 non-BUMN atau BUMN minoritas; Jumlah penangkapan aktivis demokrasi yang menolak kenaikan BBM lumayan besar. Pemerintahan Megawati juga menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali, dengan 7 kali penyesuaian harga.
- Wiranto dan Prabowo: dosa-dosa ekonomi-politik masa pemerintahan orde baru tidak akan bisa lepas dari mereka, dan tak boleh pula dilepaskan/dilupakan karena mereka bagian dari pemerintahan orde baru, terlebih lagi ada kejahatan-kejahatan HAM yang melibatkan mereka, antara lain: seperti penculikan dan penghilangan paksa aktivis 97/98, tragedi Mei 98, pelanggaran HAM di Timor Leste, serta kasus Trisakti dan Semanggi.
Dari paparan fakta-fakta tersebut, semakin jelaslah ada “maling teriak maling”, ada agen-agen neoliberal yang menuduh elit politik lainnya sebagai agen neoliberalis padahal, sesungguhnya, sama saja. Semakin terang pula, bahwa mereka yang berbicara ekonomi Pancasila ataupun ekonomi kerakyatan sesungguhnya menjadi agen-agen tuan modal internasional, mengharapkan kucuran dana dari pihak asing, dan berbagi di antara mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi haruskah rakyat terus mempercayai mereka? Cukup Sudah, Tidak!
Apakah Mungkin?
Tapi sebelum itu, ada baiknya kita kaji lebih dalam apakah konsep dan program-program mereka dapat tercapai, sekaligus apakah jalan keluar ataupun kampanye ideologis kaum borjuis melalui nasionalisme akan menjawab kebutuhan mendesak rakyat: Demokrasi dan Kesejahteraan?
Terhadap kampanye nasionalisme sebagai jalan keluar, kaum borjuis merupakan satu golongan yang paling berkepentingan dalam hal ini. Karena identitas nasional, dalam pengertian teritorial, relasi ekonomi, maupun budaya, memberikan privilege (hak istimewa) kepada kaum borjuis untuk melakukan eksploitasi dan ekspansi modalnya dalam batas-batas teritorial negeri tersebut, dan terutama dalam berhadapan dengan kaum borjuis asing yang juga memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia dari negeri tersebut. Sehingga, proteksi ekonomi, budaya dan politik yang dilegitimasi oleh nasionalisme, akan menyelamatkan akumulasi modal kaum borjuis “pribumi” dari terjangan modal kaum borjuis “asing.”
Bagi kaum borjuis (elit), nasionalisme memberikan syarat ideologis untuk melapangkan tujuan tersebut, terutama dalam pengertian untuk lebih mendukung dan mendahulukan mereka (kaum borjuis) yang sebangsa dan setanah air, sehingga mereka akan selalu berupaya mewujudkan terjadinya harmonisasi kelas dalam suatu bangsa, yang ditunjukkan (baca: dimanipulasi) dengan kecintaan mayoritas penduduk—yang terdiri dari proletariat, semi-proletariat dan borjuis kecil—kepada tanah airnya, kepada pemerintahannya dan kepada orang-orang sebangsanya, meskipun kaum borjuis nasional, tentara, ataupun alat-alat kekerasan negara lainnya ikut menindas mereka. Mereka harus tetap mencintainya meskipun proses penghisapan terus berlangsung.
Rakyat tidak memiliki kepentingan terhadap nasionalisme, karena nasionalisme tidak melenyapkan penindasan/penghisapan oleh kaum borjuis terhadap mereka. Di hadapan kaum borjuis manapun, apakah itu “pribumi” maupun “asing,” Rakyat akan tetap tertindas—dengan upah murah, waktu kerja yang panjang, buruh kontrak, ancaman pemecatan, represi fisik dan pelecehan seksual di tempat kerja. Kaum proletariat dan kaum miskin di negeri manapun memiliki persoalan ketertindasan yang serupa. Oleh karena itu, proletariat dan kaum miskin memiliki musuh yang sama, yang pertentangannya tidak dapat di damaikan selama kelas-kelas masih ada, yakni kaum borjuis.
Apakah Program-program mereka, baik itu peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan secara nasional, pembangunan infrastruktur, perlindungan terhadap sektor pertanian, kehutanan, bahkan penghapusan UU BHP dan sistem Outsourcing, dapat tercapai?
Bila dilihat paket kebijakan neoliberalisme, sesungguhnya semua itu hanya isapan jempol belaka. Kebijakan Neoliberalisme yang dibuat pada tahun 1989 lahir dari pertemuan International Finance Institution’s yang memang banyak bermarkas di Washington. WC kemudian menghasilkan 10 langkah, tiga di antaranya merupakan bagian dari kebijakan makro—yaitu disiplin anggaran, liberalisasi suku bunga, dan kebijakan nilai tukar berbasis pasar; Sedangkan tujuh langkah lain merupakan bagian dari kebijakan struktural—yaitu, privatisasi, deregulasi, liberalisasi impor, liberalisasi investasi asing langsung, reformasi perpajakan, penjaminan hak kepemilikan, dan redistribusi dana-dana publik pada sektor pendidikan serta kesehatan. Dengan menjalankan kebijakan tersebut dalam lapangan ekonomi-politik, tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tidak akan tercapai, karena tidak akan ada anggaran untuk mengembangkan Tenaga Produktif (Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Kerja, Teknologi, Modal, dll), hal itu disebabkan oleh semakin tipisnya anggaran negara karena modal lari ke luar negeri (capital flight) melalui pembayaran cicilan dan bunga utang, serta SUN. Hasilnya, negara-negara debitor, seperti Indonesia terus dan terus membayar utang mereka (debt sustainability). Jadi, UU BHP atau privatisasi pendidikan adalah konsekuensi dari konsep kebijakan pasar bebas (Neoliberalisme), karena tak cukup anggaran pendidikan untuk lembaga-lembaga pendidikan. Menghapuskan UU BHP berarti menghapuskan kapitalisasi dalam dunia pendidikan dan syaratnya adalah adanya anggaran dari pemerintah. Dan untuk memenuhi anggaran ini tidak bisa apa bila kebijakan neoliberalisme—yang berakibat pada adalah capital flight—masih digunakan. Sungguh tak mungkin. Begitu pula dalam kontrak politik penghapusan outsourcing: yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan pribumi dan asing adalah meningkatkan capital fix (kapital tetap) atau alat-alat produksi dan teknologinya. Dan agar keuntungannya tidak berkurang (dalam membiayai peningkatan kapital tetap tersebut), maka mereka harus mengurangi/menekan biaya dari capital variabel (upah buruh). Dan jalan mengoutsourcingkan buruh-buruh adalah jalan terbaik untuk tidak mengurangi akumulasi Kapital (yang diperoleh dari keuntungannya).
Dalam soal pertanian dan pemerataan pertumbuhan ekonomi: program liberalisasi perdagangan dalam General Agreement on Agriculture (WTO) mengakibatkan adanya liberalisasi beberapa produk pertanian masuk ke dalam negeri. Ketidaksanggupan produsen pertanian dalam negeri untuk bersaing dengan produk pertanian luar, karena rendahnya modal, rendahnya teknologi, fragmentasi lahan, dan minimnya infrastruktur produksi (misalnya: Jalan, Listrik, sarana angkutan), membuat banyak produk-produk pertanian dalam negeri gulung tikar dan banyak yang kemudian beralih menjadi buruh-buruh perkotaan dan migran. Selain itu, menyebabkan hilangnya otoritas monopoli dari pemerintah sehingga pula menyebabkan ketidakstabilan pasokan barang dan harga dipasar, serta praktek penyelundupan (smugling) dan spekulan produk—yang membuat para pedagang-pedagang dan spekulanlah yang mengatur pasar, baik dalam jumlah pasokannya maupun permainan tingkat harganya. Singkat kata, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian serta pemerataan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai dalam rumus ekonomi neoliberal, sebab yang dibutuhkan adalah perubahan yang mendasar dari struktur ekonomi nasional, yang mengharuskan investasi besar-besaran pada pembangunan Tenaga Produktif!
Kemudian, elit-elit itu berbicara soal nasionalisme ekonomis dan penggabungan konsep kapitalisme dan sosialisme (Prabowo), atau biasa dikenal sebagai Nasionalisme Sosial Demokrat (suatu konsep ekonomi jalan tengah) untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Mungkinkah? Sama sekali TAK MUNGKIN, karena: nasionalisme ekonomis membutuhkan banyak hal, antara lain mobilisasi massa, karakter politik yang Mandiri dan Anti Imperialis, didukung dengan manajemen yang baik dan profesional, modal, dan teknologi modern. Dan syarat fundamental tersebut tidak ada dalam rekam jejak elit-elit politik hari ini, keseluruhan dari mereka hanyalah menjadi calo bagi modal asing, menghamba kepada asing untuk modal, teknologi, majemen dan jaringan. Apalagi, mayoritas di antara elit-elit pada hari ini tidak memiliki kekuatan mobilisasi massa yang jelas, sebab, massa mereka bukanlah massa yang di ikat dengan ideologi-politik melainkan dengan pamor dan patronisme, jadi bagaimana mungkin melawan modal internasional (yang ingin bebas leluasa mencaplok kekayaan negeri ini).
Kemudian, Nasionalisme Sosial Demokrat juga sama sekali TAK MUNGKIN, karena: konsep sosial demokrat yang menekankan pada pajak dari perusahaan—yang sesungguhnya diambil dari hak upah para buruhnya—yang akan didistribusikan bagi subsidi-subsidi sosial tidak bisa dilaksanakan karena mayoritas dari modal perusahaan “pribumi” rendah kapasitasnya, keuntungannya tidak besar (terlebih dijalankan dengan kurang profesional) sehingga bisa berakibat bangkrutnya berbagai perusahaan “pribumi”, yang banyak di antaranya terlilit utang karena tingginya suku bunga bank. Jalan lain (dalam konsep Sosial Demokrat) adalah dengan mengenakan pajak atau bagi hasil kepada perusahaan-perusahaan asing ataupun produk-produknya, tetapi konsep ini pun hanya bisa dijalankan dengan adanya mobilisasi massa dan karakter serta kekuatan politik yang anti imperialis sebab, dengan krisisnya kapitalisme, korporasi internasional paling denggan dengan pengurangan keuntungan mereka ataupun pembatasan area penghisapan mereka. Dan sejauh ini, tak ada, sekali lagi, rekam jejak elit-elit politik tersebut berani melawan Imperialis, semuanya berkolaborasi dengan Imperialisme untuk mendapatkan ceceran utang dan jaringan ekonomi.
Jika Elit Politik tak mampu memberikan Demokrasi dan Kesejahteraan, lalu siapa dan bagaimana bisa diberikan?
Sekali lagi, Persatuan Gerakan Mandiri (Non Kooptasi-Non Kooperasi) dan Rakyatlah yang bisa menjadi solusi. Agar dapat menjadi Bangsa yang Besar dan juga internasinoalis, bangsa ini harus digembleng. Digembleng melalui perjuangan melawan dan menyingkirkan Imperialisme, membebaskan dirinya (bangsanya) dari penghisapan modal internasional; menjalankan Pembebasan Nasional! Kenapa? Karena, sejatinya bangsa ini belum terbebas dari cengkraman modal asing; belum terbebas dari penjajahan. Penjajahan masih ada dan nyata, melalui seluruh kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh elit-elit politik agen Imperialis di lembaga-lembaga Negara yang menyengsarakan rakyat negeri ini, membuat rakyat di negeri ini terpuruk, terjebak dalam jurang kemiskinan, serta hilang kebudayaan majunya: kebudayaan mandiri. Dan perjuangan Pembebasan Nasional ini tidak bisa disandarkan pada kekuatan elit, karena mereka tak memiliki kapasitas untuk itu—meskipun juga dirugikan oleh Imperialisme—mereka malah menjadi agen/calo/komprador Imperialisme.
Kemenangan SBY-Boediono merupakan tamparan bagi kaum gerakan dan rakyat. Tamparan karena sebagian rakyat masih (“terpaksa”) mau memilih SBY kembali—melalui logika pragmatis mereka (memilih yang terbaik dari yang terburuk) karena tidak ada ketersediaan alternatif dan, cilakanya, gerakan tidak menyediakan diri sebagai alternatif. Gerakan terpecah dapat dibedakan menjadi: kelompok yang berkolaborasi dengar elit dan yang tetap percaya pada garis kemandirian politik. Sayangnya, di antara kelompok-kelompok gerakan yang masih meyakini politik alternatif, Politik Kemandirian, tidak segera bersatu secara nasional, menunjukkan alat, program dan metode politiknya sehingga rakyat (yang tetap mau memilih) dapat melihat opsi politik lainnya—selain terlibat dan ikut memilih dalam panggung hegemoni politik elit (pemilu 2009). Kelompok Gerakan yang Mandiri mestinya sadar bahwa ada kehendak perubahan dari Rakyat, yang bisa ditangkap/dimengerti oleh elit-elit politik (seperti Mega Prabowo) dan hendak dimanipulir demi kepentingan kelas mereka. Dan kehendak perubahan itu seharunya terus didorong maju, menjadi tindakan politik, menjadi perubahan yang radikal dan mendasar: Revolusi. Tapi hal tersebut membutuhkan konsentrasi dan sentralisasi kekuatan politik kelompok gerakan mandiri dalam Front Persatuan Progressif. Tanpa sentralisasi kekuatan, kelompok gerakan mandiri sulit untuk memberikan pengaruh politiknya. Oleh karena itu, Front Persatuan yang berkarakter Progressif harus menjadi Pusat Politik, pusat dari segala aktivitas politik, aktivitas kebudayaan, aktivitas organisasi, aktivitas propaganda, dan dari basis Front Persatuan inilah alternatif bisa disediakan. Tanpa itu, omong kosong!
Front Persatuan inilah yang selanjutnya menjadi alat politik dalam perjuangan pembebasan nasional, perjuangan melawan Imperialisme, perjuangan menyingkirkan dominasi modal internasional yang terus menghisap dan menindas. Front persatuan inilah yang akan menjadi alat untuk mengalahkan dominasi dan hegemoni Imperialis melalui “boneka-bonekanya”: Sisa-Sisa Ordebaru, Militer, Reformis Gadungan dan Milisi Sipil Reaksioner. Bahkan Front Persatuan inilah yang menjadi pusat untuk mengembangkan kebudayaan Maju/Progressif—yang sebelumnya dibumihanguskan oleh 32 tahun kekuasaan Ordebaru—melalui: Aksi Massa, Vergadering, Slogan, Bacaan, Teatrikal, Karya-Karya Seni dan Sastra sehingga nilai-nilai progressif tumbuh-kembang seiring dialektika perjuangan Pembebasan Nasional.
Tanpa Persatuan, Tanpa Pembebasan Nasional, cita-cita yang Sesungguhnya (Sosialisme) tidak akan tercapai. Tanpa persatuan dan pembebasan nasional, cita-cita untuk mewujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis, Kesehatan Gratis, perumahan, transportasi, minyak murah dan massal, Kenaikan Pendapatan dan Lapangan Pekerjaan, Pengadilan Kejahatan HAM dan Pembubaran Komando Teritorial tidak akan tercapai. Dan Sosialisme sebagai Jalan Keluar krisis kapitalisme akan tercapai apabila Pembebasan Nasional diletakkan sebagai basis Revolusi Sosialis. Revolusi yang tidak hanya menyingkirkan dominasi Imperialisme di negeri ini ataupun menggantikan kekuasaan agen-agen Imperialis tetapi juga mengkolektifisasi alat-alat produksi ke tangan Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin dan mendistribusikan hasil-hasilnya kepada rakyat. Sosialisme adalah Jawaban terhadap krisis kapitalisme, jawaban atas semakin senjangnya tingkat harga dan nilai suatu komiditi sehingga masyarakat tak mampu menjangkaunya (rendah daya beli), dan jawaban atas melimpahnya produk-produk kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) tetapi banyak rakyat miskin yang belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya.
Maka dari itu, Front Persatuan yang Mandiri, Anti Imperialis, Demokratik haruslah memiliki program dan metode politik yang kongkret yang dapat menghantarkan perjuangan hingga ke “gerbang” yang sebenarnya: Sosialisme. Dan hal itu terjadi, sekali lagi, apabila Front Persatuan ini dapat menjadi Pusat Politik untuk merebut kekuasaan dari tangan agen-agen Imperialis, menasionalisasi aset-aset asing, berani mensentralisasi alat-alat produksi yang sebagian besar di kuasai oleh asing, dan menangkap, mengadili, serta menyita kekayaan para koruptor (termasuk almarhum Soeharto dan Kroni-Kroninya) ke tangan pemerintahan yang didirikan oleh persatuan mandiri tersebut. Selain itu, menjalankan kekuasaannya secara demokratik dan menjawab hambatan-hambatan bagi perjuangan menuju Sosialisme: Kebudayaan Maju, dan Peningkatan Tenaga Produktif serta Kesadaran Politik, agar Industrialisasi Nasional yang modern, profesional serta ekologis dapat mendistribusikan hasil-hasilnya kepada rakyat.
Selesai.