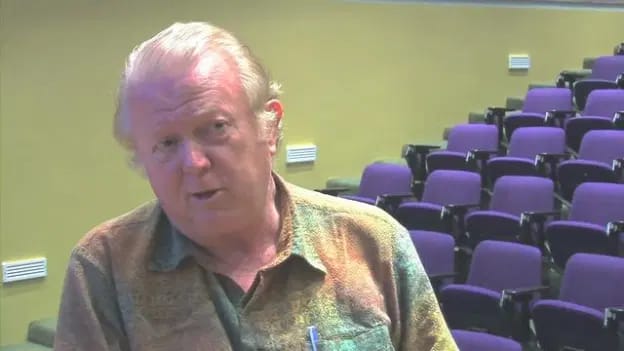Oleh: DR. Max Lane
Artikel ini merupakan salah satu Bab dari buku yang diterbitkan pada 2014, berjudul “Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi” disusun oleh Usman Hamid, AE Priyono. Artikel ini dirampungkan pada pertengahan 2013. Penerbitan artikel ini telah seijin penulis artikel dengan tujuan untuk pendidikan dan penyadaran.
Mundurnya Presiden Suharto pada Mei 1998 di bawah tekanan gerakan pro-demokrasi mengakhiri 33 tahun kediktatoran militeristik. Suharto mundur dari kedudukan sebagai Presiden karena terpaksa oleh tekanan dahsyat sebuah gerakan politik. Suharto sendiri tidak sempat mengatur proses kemunduran dan suksesinya. Ketika dia menyelenggarakan sebuah kabinet pada awal 1998, dia masih berpikir akan tetap berkuasa terus. Tetapi dia salah hitung. Yang dia hadapi saat itu adalah munculnya sebuah gerakan politik pro-demokrasi yang menuntut berbagai perubahan secara besar-besaran. Pada bulan April dan Mei 1998, Suharto dikhianati dan ditinggalkan teman-teman kekuasaannya, mulai dari menteri-menteri sampai pimpinan militer. Mereka semua takut bahwa tuntutan perubahan dari gerakan politik itu akan semakin meluas dan mengalami radikalisasi kalau situasi tidak segera dibikin tenang. Suharto dikorbankan, dan dia sendiri akhirnya mau mengakhiri kekuasaannya. Tapi ini dilakukan demi menyelamatkan kedudukan seluruh kelas-penguasa Indonesia sebagai suatu kelas yang berkuasa.
Skenario ini berarti bahwa proses berakhirnya kediktatoran di Indonesia memiliki dua sifat utama. Pertama, terjadi sebuah penguatan gerakan masyarakat yang berhasil mengancam kelas yang berkuasa sehingga kelas tersebut terpaksa mengakhiri sistem kekuasaannya yang lama, yakni sistem kediktatoran. Kedua, kelas berkuasa sendiri tetap berhasil mempertahankan kekuasaannya, meski dalam situasi tidak sekuat sebelumnya dalam menghadapi masyarakat dan tanpa mereka sendiripun “dipimpin” oleh kekuatan kediktatoran lagi.
Adalah kombinasi dari dua ciri ini yang mendefinisikan sifat-sifat periode pasca kediktatoran antara 1998-2008, sebuah periode selama satu dasawarsa yang mungkin bisa disebut sebagai “periode reformasi.” Kalau dua hal di atas diamati sebagai sebuah kesatuan, terjadi situasi di mana kelas berkuasa Indonesia mengalami pelemahan paling serius sebagai kekuatan politik dibandingkan dengan yang dialami kelas-kelas lain. Tetapi pelemahan itu tidak diakhiri dengan peniadaan atau pergantian karena kemenangan gerakan pro-demokrasi segera mengalami demobilisasi. Gerakan pro-demokrasi yang berkembang pesat antara tahun 1996-1998 menuntut turunnya Suharto dan terselenggarakannya “demokrasi,” juga tuntutan agar militer mundur dari keterlibatannya dalam politik, yaitu sebagai pelaku represi. Tetapi ketika tuntutan ini tercapai (kecuali di Papua), gerakan mengalami demobilisasi. Dan inilah ironisnya: pada pada saat elite politik dan bisnis Indonesia mengalamai pelemahan kekuatan, gerakan politik yang tadinya berhasil mengalahkannya berhenti bergerak. Ironi ini sebenarnya ada penjelasannya. Dan seharusnya kita tidak perlu kaget dengan situasi tersebut.
Warisan Kehidupan Politik di Bawah Orde Baru
Salah satu ciri khas sistem politik Orde Baru ialah ditiadakannya kehidupan politik untuk kelas-kelas sosial Indonesia, baik untuk kelas kapitalis maupun kelas proletar, juga kelas petani. Sebelum 1965 semua kelas sosial Indonesia mengalami peningkatan kemampuan berorganisasi, termasuk berorganisasi secara politik. Penguatan kapasitas berorganisasi itu dilakukan melalui partai politik dan organisasi massa yang berafiliasi atau bekerja-sama dengan partai-partai. Ada kelas-kelas sosial proletar dan petani yang sudah bergerak di bawah “bendera” masing-masing; dan ini berarti mencerminkan munculnya kesadaran kelas yang meluas, baik yang revolusioner maupun yang belum. Bendera mereka juga relatif bervariasi, seperti sosialisme, komunisme, atau marhaenisme. Ada juga yang menjalankan kehidupan politik yang aktif tetapi bergerak di bawah bendera non-kelas, seperti berbasis agama ataupun nasionalisme (entitas-entitas yang tidak mengakui pertentangan kelas). Kecenderungan yang sama juga terjadi pada kelas-kelas kapitalis, yang pada waktu itu masih sangat kecil dan masih dalam proses pembentukan. Ada yang sarat kesadaran kelas, seperti di kalangan beberapa faksi borjuasi dengan semboyan “revolusi sudah selesai,” atau yang lain dalam jargon “jangan berpolitik” seperti ideologinya Manikebu (Manifesto Kebudayaan), ada juga yang menggunakan ideologi agama. Itulah suasana pada masa pra Orde Baru. Semua kekuatan sangat aktif secara politik. Kehidupan politik negeri sangat menggairahkan, melibatkan jutaan orang berdiri di atas keaktifan partai dan organisasi massa, termasuk dengan semua kontradiksinya, kelemahannya, dan keterbatasannya.
Sebaliknya, Orde Baru berdiri di atas program pembunuhan terhadap kehidupan politik dan ideologi yang sudah berkembang selama 50 tahun. Pembunuhan fisik, terror massal, larangan-larangan dan sensor politik dan budaya, kebijakan floating-mass dan monoloyalitas, pengebirian partai, kediktatoran dan monopoli tafsir atas sejarah serta penghapusan memori bangsa. Di atas semua itu kontrol ketat terhadap politik sehari-hari merupakan bagian-bagian dari program pembasmian kehidupan politik dan ideologi. Ini dilakukan juga terhadap elemen kelas kapitalis. Misalnya, Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang pro-kapitalisme versi sosial-demokrasi Barat, tetap tidak diizinkan berdiri. Masyumi yang giat melawan ideologi-ideologi anti-kapitalis sebelum 1965 hanya dizinkan aktif lagi dengan syarat harus ganti nama atau dengan pimpinan lama yang tak boleh aktif. Sistem kepartaian sendiri tidak mendorong kelas yang manapun melakukan pengorganisan diri di bawah bendera apapun. Sementara itu pemerintah, melalui Golkar (dan Kopkamtib), mengatur, mendikte, dan melakukan pengawasan ketat terhadap kehidupan partai politik. Mereka menyelenggarakan politik “floating mass” (massa mengambang) agar massa dan rakyat diasingkan dan disingkirkan sejauh-jauhnya dari politik.
Situasi ini berlangsung lama sekali – lebih lama sebenarnya daripada yang tercermin dalam perhitungan jumlah tahun. Orde Baru berlangsung 33 tahun – memang lama sekali, termasuk beberapa generasi. Mungkin ada 70% penduduk Indonesia yang hanya pernah mengalami situasi politik Orde Baru dan yang diwariskan Orde Baru. Bahkan mungkin 80%. Kelompok ini tentu saja telah dikosongkan dari memori-memori besar mengenai proses penting pembentukan bangsa. Dan bukan hanya itu. Pada tahun 1965, Indonesia sebagai negeri baru terbebas 20 tahun dari penjajahan; dan dari 20 tahun itu lima tahun terakhir mulai terseret ke suasana monolitik kediktatoran Soekarno. Dengan kata lain, proses pembentukan Indonesia yang sebenarnya-benarnya hanya sempat berlangsung 15 tahun, antara 1945-1959. Periode 15 tahun itupun adalah periode ketika visi-visi dipertarungkan. Karena itu bisa dikatakan bahwa proses pembentukan yang sebenarnya belum lagi dimulai: masih terjadi pertarungan. Sehingga ketika Orde Baru berdiri sejak 1965 dan mulai menyelenggarakan sistem politiknya (yang anti-kehidupan politik) selama 33 tahun kemudian, Suharto dan Orde Baru sebenarnya mutlak telah menghentikan proses pembentukan bangsa. Yang dilakukan Orde Baru adalah pembasmian Indonesia. Dengan pandangan ini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya pada 1998, Indonesia memulai kembali dari nol, khususnya dari segi visi-visi yang belum selesai dipertarungkan.
Orde Baru mewariskan situasi di mana tingkat kehidupan berorganisasi politik masyarakat, dari semua kelas, sangat rendah sekali, bahkan hampir tidak ada. Bukan hanya organisasi dan lembaganya tidak jalan, tetapi tradisipun sudah tiada. Tiada lagi ada ingatan atau memori sejarah hebat mengenai gerakan politik Indonesia mulai dari Sarekat Dagang Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Masjumi, maupun mengenai zaman pertarungan masa depan negeri, 1945-1965. Kadang-kadang baik aktivis maupun pengamat suka menyebut adanya “fragmentasi” dalam perpolitikan Indonesia dan kemudian mencari penyebabnya dalam kehidupan politik dan ekonomi pasca Orde Baru. Ini keliru total. “Fragmentasi” – atau bahkan atomization – perpolitikkan Indonesia adalah produk langsung 30 tahun lebih kelas-kelas sosial Indonesia tidak menjalankan atau memiliki kehidupan politik ataupun ideologi. Bahkan memori tentang kehidupan politik dan ideologi masa 1900-65 sudah tidak ada lagi penghayatannya.
Yang ada di antara sebagian orang ialah memori tentang kehidupan politik periode 1996-1998 (dan untuk yang aktivis pelopor adalah 1989-1998). Tetapi pengalaman ini tidak mungkin membentuk sebuah hegemoni budaya politik baru. Ada beberapa faktor mengapa demikian. Pertama, masa waktu yang hanya 3 tahun terlalu pendek untuk membentuk sesuatu apapun yang hegemonik, kuat, berskala nasional dan memilki daya tahan – apalagi menghadapi semua produk Orde Baru hasil 33 tahun kekuasaan. Kedua, 99% rakyat yang mengalami dan terlibat dalam organisasi politik selama periode 90an pada kenyataannya hanya “berorganisasi” dalam wadah dan kegiatan yang bersifat sangat sementara. Ini bisa dalam bentuk komite-komite aksi untuk isu yang hidup hanya beberapa minggu, ataupun yang paling sementara gerakan massa merespons selebaran yang hanya bisa bertahan satu hari. Dengan situasi sangat represif dan tanpa ada organisasi massa politik yang sudah berdiri, juga tanpa memori dan tradisi, ini tidak mengherankan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memang memanfaatkan sisa-sisa memori pra-65, melalui nama dan simbol Sukarno, sekaligus juga struktur fisik organsisasi PDI yang diizinkan selama Orde Baru. Tetapi ini tidak pernah dimanfaatkan maksimal, dan yang tidak maksimalpun juga hanya 1996-1997, dua tahun.
Pada tahun 1998 Suharto terpaksa turun dan kediktatoran memang berakhir. Kelas berkuasa yang selama 33 tahun bisa mengusahakan kehendaknya dalam suasana kediktatoran mulai menghadapi situasi baru yang tak lagi mampu mereka kendalikan. Mereka terpaksa berakomodasi dengan proses politik demokrasi parlementer dalam sebuah masyarakat di mana tingkat kehidupan berorganisasi dan berpolitiknya sangat rendah, bahkan tradisinya dan memorinya juga sudah hampir punah. Dengan melihat kenyataan ini saja kita sudah bisa menduga bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bermasalah. Demokrasi yang ditunggangi oleh elite diktatorial masa lalu. Bagaimana mengubahnya? Situasi akan berubah jika proses-proses demokrasi parlementer (terutama partai dan pemilihan umum) bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor masyarakat. Sejauh mana itu bisa terjadi akan tergantung pada sejauh mana kelas-kelas sosial (atau sektor-sektor kelas sosial) mulai mengorganisir diri kembali. Masalahnya adalah bahwa proses ini, khususnya untuk kelas sosial proletar dan petani, betul-betul dimulai dari hampir nol, meski bukan total-zero, tanpa ada tradisi, tanpa memori, tanpa pengalaman. Jadi perubahan tidak bisa terjadi serta-merta secara langsung dan cepat.
Kehidupan Partai dan Kelas Pasca Orde Baru
Kalau kita mau pakai “pisau analisa kelas,” salah satu aspek dari turunnya Suharto dan berakhirnya kediktatoran ialah bahwa kekuasaan politik lapisan kapitalis kroni sangatlah berkurang. Perubahan ini memang dengan sendirinya terjadi serta merta akibat turunnya Suharto dan berakhirnya kediktatoran. Yang namanya “kapitalis kroni” hanya dimungkinkan kalau ada kediktatoran. Kroni adalah kerabatnya diktator yang maju bisnisnya dikarenakan perlindungan dan permanjaan dari sang diktator. Selama Orde Baru, golongan kapitalis kroni ini menjadi basisnya rezim, dibeking oleh kapital besar Amerika, Jepang dan Eropa Barat, dengan tentara sebagai alat represifnya yang utama.
Dengan berakhirnya kediktatoran, kroni kapitalis kehilangan kedudukannya sebagai “kroni.” Mereka harus berpolitik dengan cara baru. Kecenderungan utama di kalangan ini ialah menguasai sebuah partai yang bisa berpartisipasi dalam pemilu. Aburizal Bakrie menguasai Golkar; Surya Paloh Nasdem; Hasyim dan Prabowo Djojohadiskusumo menguasi Gerindra dan seterusnya. Bukan hanya itu. Semua konglomerat besar di Indonesia pada hakekatnya tercipta lewat proses-proses kronisme dan kolusi. Mereka semua ketagihan fasilitas kroni. Tetapi bagaimana bisa kembali menjadi kroni dalam situasi di mana tak ada kediktatoran yang stabil? Jelas sekali apa solusinya! Mereka sendiri harus menjadi presiden. Makanya mantan kroni-kroni terbesar Indonesia semua berambisi menjadi calon Presiden.
Strategi figur-figur konglomerat ini untuk mejadi presiden adalah konsekuensi kronisme, juga sekaligus mencerminkan dan menjadi bagian kelemahan mereka sendiri. Para kapitalis konglomerat hitam ini tidak bisa membentuk blok politik dalam memperjuangankan kepentingan bersamanya – mereka justeru saling bersaing. Ini merupakan sebuah kelemahan besar dan terwujudkan dalam terpecahnya Golkar, sebagai partainya kaum kroni sebelumnya. Ada foto yang sedang beredar luas di facebook: Surya Paloh, Bakrie, Prabowo, (dan politisi Akbar Tanjung) semua lagi berjabatan tangan. Sekarang mereka sudah punya partai mereka sendiri-sendiri. Kelemahan berikutnya lebih berkaitan dengan proses formal yang menjadi landasan dari demokrasi parlementer. Sekarang bukan hanya ada pemilihan umum untuk berbagai lembaga perwakilan, nasional maupun lokal, tetapi juga ada pemilihan langsung untuk presiden, gubernur, bupati dan walikota. Karena semua pemilu ini terjadi dalam suasana bebas represi, money politics cara lama juga tak berlaku. Dulu orang yang diberi uang untuk suara harus bisa sekaligus terancam oleh teror – sekarang, itu tidak berlaku lagi. Ini berarti seorang kroni yang mau mengkronikan dirinya kembali dengan meraih jabatan presiden harus memenangkan persaingan popularitas dengan calon lain. Sebagai figur konglomerat hitam ataupun represi masa Orde Baru, semua kroni ini tidak populer. Dalam semua polling saat ini mereka kalah dengan politisi mantan pengusaha mebel Solo – Jokowi; ataupun politisi anak perempuan Sukarno – Megawati.
Figur-figur ini menguasai banyak dana dan kapital, juga media yang belakangan memang mereka beli dan kuasai. Mereka dan partainya tetap signifikan dalam pencaturan politik kekuasaan Indonesia. Tetapi karena mereka terpecah, saling bersaing dan juga menghadapi masalah popularitas dalam suasana bebas repressi, mereka sama sekali tidak bisa mendikte lagi bagaimana kekuasaan politik akan berkembang.
Partai Politik dan Pengusaha Lokal Pasca Orde Baru
Ada satu aspek lagi dari kapitalisme kroni Indonesia yang sangat ikut menentukan perpolitikan kelas kapitalis Indonesia di era pasca kediktatoran. Ekonomi Indonesia sendiri adalah sebuah ekonomi warisan kolonialisme (zaman Hindia Belanda) yang sangat under-developed. Meskipun sektor manufaktur sudah bertumbuh dibanding dengan sebelum tahun 1965, untuk sebuah negeri modern berjumlah penduduk 235 juta orang, Indonesia bisa dikatakan sangat under-industrialised. Pendapatan per kapita juga masih di bawah US 4.000 dolar per tahun. Kapitalisme tanpa industri yang signifikan, baik dalam skala maupun jenisnya, ini hanya bisa melahirkan kapital besar melalui kronisme dan kolusi. Di Indonesia kelas kapitalis berkembang menjadi dua golongan utama selama Orde Baru dan itu berlangsung sampai sekarang: kapitalis kroni, dan kapitalis lokal. Dalam dekade terakhir ini mungkin ada juga kapital-kapital baru yang berkembang di luar dua golongan ini – misalnya Kapital baru di bidang penerbangan – tetapi inipun masih di tahap awal.
Kapitalis lokal adalah pengusaha yang skala kegiatannya terbatas di kebupaten atau provinsinya, atau antar-provinsi di sekitarnya. Hanya 10% dari perusahaan Indonesia yang memiliki lebih dari 20 pegawai; 77% hanya memiliki 10 pekerja atau kurang dari itu. Karena berskala kecil, sudah hampir pasti bahwa semua perusahaan ini memang hanya bergerak di wilayah lokal mereka. Sejak para kapitalis kroni kehilangan diktator pelindungnya dan kedudukan politiknya melemah, kapitalis lokal mendapatkan ruang gerak yang membesar dibanding sebelumnya. Teriakannya untuk federasi, otonomi lokal atau desentralisasi cepat bergema selama 1999-2001. Gerakan pro-demokrasi tahun 1990an jarang membicarakan dan tak pernah menuntut desentralisasi; dan baru diketahui belakangan ternyata tuntutan itu berasal dari elite-elite lokal. Mereka memenangkan tuntutan itu dan undang-undangnya cepat lolos – sebagian karena dukungan lembaga-lembaga donor yang memang sejalan ideologi post-Washington consensus. Tetapi ini tidak mengherankan. Sejak tahun 1999 sebagian besar partai politik memang menjadi makin tergantung pada pengusaha lokal. Bahkan di partai di mana seorang mantan kroni menduduki puncaknya, partai inipun menjadi sangat butuh partisipasi pengusaha lokal dalam pemilihan-pemilihan, apalagi sejak ada pemilukada. Bahkan sering juga sekarang pengusaha lokal, keluarga pengusaha lokal atau pejabat kroninya tertarik untuk maju menjadi gubernur, walikota atau bupati.
Semua kegiatan pemilihan dan kampanye ini tersalurkan lewat partai-partai politik. Partai politik menjadi alat konglomerat mantan kroni yang bekerjasama dengan para pengusaha lokal – yang merupakan 95%+ jumlah kapitalis di Indonesia. Akibat dari peta ekonomi-politik kepartaian ini ialah bahwa sampai sekarang mayoritas partai yang agak “besar” memiliki kecenderungan untuk berbasis di daerah-daerah. Karena sebagian besar kapitalis Indonesia tidak berkembang dan beraktifitas dalam skala dan wawasan nasional, maka begitu juga partainya. Meskipun partai-partai yang lolos verifikasi untuk ikut pemilu sudah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai partai nasional (kecuali sebagian partai di Aceh), kenyataannya ialah bahwa hasil pemilu selalu menunjukkan bahwa masing-masing partai memiliki basis kuat di daerah-daerah tertentu. Salah satu akibat dari semakin luasnya ruang gerak politik kaum pengusaha lokal dalam situasi di mana industrailisasi yang sesungguhnya masih tidak berkembang ialah meledaknya sejenis kronisme di tingkat lokal. Korupsi merajalela dan mengalami lokalisasi. Menurut Departemen Dalam Negeri, 20 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota, 20 wakil walikota, 2.545 anggota DPRD Provinsi, dan 431 anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota tersangkut kasus korupsi.
Dalam situasi seperti ini bagaimana hubungan partai-partai ini dengan rakyat banyak, yaitu rakyat miskin yang merupakan mayoritas terbesar penduduk Indonesia? Dengan adanya pemilukada dan pemilihan umum, popularitas memang menjadi faktor menentukan dalam perpolitikan Indonesia. Tetapi secara garis besar, partai-partai semakin tidak populer dan jumlah suara golongan putih meningkat. Partai-partai merespon keadaan ini dengan menunjuk dan mengangkat para selebriti atau figur pengkhotbah pop dari dunia agama untuk ikut kampanye dan menjadi calon-calon legislatif. Partai-partai yang dikuasai figur konglomerat menghambur-hamburkan uang untuk iklan. Tetapi semua ini tidak terlalu mengubah situasi. Selama periode 2000-2012 semakin banyak orang melihat bahwa tidak mungkin akan ada perubahan yang benar-benar bisa mengubah keadaan melalui proses-proses pemilu. Demokrasi elektor masih hanya menjadi instrumen elite, dan kini meluas di kalangan elite – birokrat ataupun pengusaha – tingkat lokal.
Transisi Memasuki Periode Pasca Pasca-Orde-Baru
Tetapi pada tahun 2013, 15 tahun sesudah turunnya Suharto, ada tanda-tanda bahwa situasi yang digambarkan di atas sedang mengalami berbagai pergeseran. Saya sendiri memperkirakan akan terjadi sesuatu yang berubah secara radikal selama dekade mendatang. Tentu saja perubahan seperti itu butuh proses yang sering kontradiktif karena melibatkan perombakan total atas suasana yang ada sekarang.
Sebelum kita teruskan diskusi tentang kemungkinan perubahan di atas, perlu ditegaskan lebih dulu bahwa perubahan yang bisa diharapkan ini bukan sejenis perubahan yang tercerminkan pada gejala Jokowi (Joko Widodo) di Solo dan Jakarta. Popularitas Jokowi di Solo yang sempat menghasilkan dukungan pemilih 91%, dan kemampuannya mengalahkan secara elektoral inkumben Fauzi Bowo untuk menjadi Gubernur DKI ada hubungannya dengan proses-proses yang berkembang menuju perubahan. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa itu tidak mewakili isi akhir perubahan yang saya bayangkan. Di satu sisi, munculnya Joko Widodo, seorang pengusaha lokal terkemuka dari Surakarta, itu mencerminkan kecenderungan yang saya diskusikan di atas yakni semakin luasnya ruang gerak para pengusaha lokal yang mendapatkan, tanpa hubungan sebelumnya, posisi strategis di sebuah partai politik sehingga memungkinkan dia naik menjadi penguasa lokal. Saat ini Joko Widodo, karena popularitasnya, ikut dibicarakan sebagai calon potensial untuk Presiden. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah Indonesia bahwa seorang pengusaha lokal dianggap pantas – oleh sebagian masyarakat – mejadi Presiden Republik Indonesia. Ini mencerminkan situasi baru di mana pengusaha lokal bisa meraih kesempatan-kesempatan baru yang sangat besar.
Tetapi popularitasnya sesungguhnya mencerminkan hal lain. Pertama, Widodo berhasil membaca kebencian masyarakat luas terhadap gaya pejabatisme yang sangat egotistik, yang merupakan kecenderungan umum kalangan politikus. Widodo memutuskan untuk tidak pasang poster atau gambar dirinya sebagai walikota. Dia sering berkunjung langsung ke kampung-kampung untuk ketemu dengan para pemilih. Kedua, selama menjadi walikota Solo, Widodo tidak terlibat masalah korupsi. Dua hal kunci ini kemudian dibarengi dengan kenyataan bahwa Widodo lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan yang disebut – kalau kita pinjam istilah Bank Dunia – “social safety net.” Kebijakan ini berarti bahwa pemerintah harus menyediakan dana subsidi kesejahteraan untuk lapisan miskin yang paling bawah. Selama 8 tahun terakhir ini penghasilan pemerintah nasional Indonesia membludak karena revenue dari penjualan batu bara dan jenis-jenis ekonomi ekstraktif lainnya. Sebagian uang ini disalurkan oleh pemerintah nasional ke kabupaten dan kotamadya. Anggaran kotamadya Solo tumbuh 500%. Widodo memiliki kesempatan untuk meneteskan sebagian darinya ke lapisan paling miskin. Kombinasi dari semua faktor ini menjadi basis dari popularitasnya di Solo, yang kemudian dimanfaatkan sebagai prestasi yang dijual selama kampanye untuk Gubernur DKI.
Tetapi ada aspek lain dari cara berpolitik Widodo yang sangat reaksioner yang sebenarnya justru memperkuat warisan utama budaya politik Orde Baru. Memang Widodo memakai gaya politik yang sangat berlainan dengan gaya pejabatisme Orde Baru dan pasca Orde Baru. Kedua, gaya ini merespons budaya patron-klien yang masih sangat kuat di Indonesia. Gaya pertama menekankan kewibawaan, otoritas, dan kekuatan politik “sang bapak” – kombinasi antara gertak-dan-paksa. Gaya seperti ini selama 20 tahun terakhir ini sudah dikenal sebagai gaya pejabat dan politikus korup. Dalam sebuah masyarakat di mana budaya dan mental patron-klien masih kuat, “kelas klien” – rakyat banyak yang belum bangkit secara politik karena belum sadar dan mampu mengaktualisasikan hak-haknya – selalu mencari seorang patron, seorang Bapak yang baik, seorang pelindung yang “kerakyatan” yang ingat dan mau dekat dengan rakyat. Persis pada kebutuhan akan adanya “patronase alternatif” itu Jokowi muncul, apalagi kemudian ditopang oleh kebijakan Bank Dunia untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penyedia “jaringan keamanan sosial.” Joko Widodo memadukan gaya penampilan seorang Bapak yang bukan hanya baik hati dan jujur, tetapi juga menyediakan perlindungan langsung untuk meredam penderitaan lapisan paling bawah. Dengan kata lain ia melayani kehausan sebagian masyarakat banyak akan seorang patron yang kerakyatan. Dengan gaya baru ini, dia sebenarnya hanya memperbarui hubungan-hubungan patronase dan pola-pola baru klientelisme.
Biarpun gaya Widodo merupakan tantangan buat politikus gaya lama, semua metode berpolitik yang mengakomodasi mental patron-klien pada dasarnya hanya memperkuat warisan budaya politik Orde Baru. Budaya patron-klien itulah yang selama ini paling menghambat partisipasi rakyat untuk menjadi lebih aktif secara politik. Seperti saya katakan di awal esai ini, warisan utama Orde Baru adalah membunuh kebiasaan kelas-kelas sosial untuk berorganisasi secara politik, dan menumpasnya sampai ke memori-memorinya yang paling dasar. Segala perpolitikan yang memanfaatkan mental patron-klien tanpa menantangnya justeru memperkuatnya. Jokowi tidak pernah mengajak kaum klien (rakyat kecil) untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan perlawanan menghadapi kekuatan kaum patron. Ia juga tidak terlihat pernah mau mendorong organisasi komunitas untuk memperkuat pengorganisasian politik di tingkat rakyat jelata yang mendukungnya. Yang dia lakukan hanya mendorong komunitas untuk melakukan politik lobby pada patron; dan ini tetap menjadi bagian dari sebuah proses yang memperkuat mental patron-klien dengan segala ketergantungan kaum klien pada kaum patron. Jelas bukan seperti ini yang dibutuhkan bagi perubahan politik yang mendasar. Tetapi kita hendak mengatakan di sini bahwa pengalaman Indonesia dengan gejala Jokowi ini adalah pengalaman transisional, sebuah proses yang harus dilewati untuk menuju yang akan melebihinya. (Bersambung)