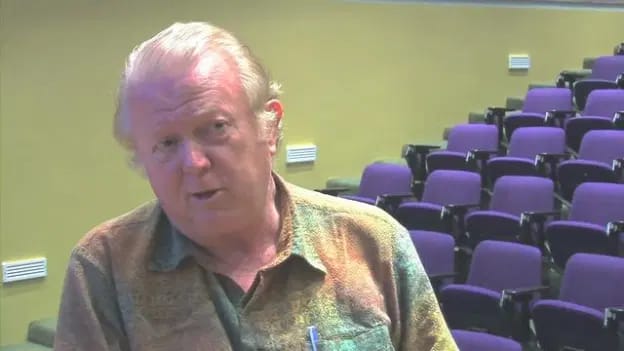Indonesia berdiri sebagai nasion karena ide-ide yang tumbuh di zamanaufklärung yang menghargai kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Tapi kini semua berada dalam ancaman. Indonesia berdiri sebagai nasion karena ide-ide yang tumbuh di zamanaufklärung yang menghargai kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Tapi kini semua berada dalam ancaman.
Sebagai negeri majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa dan agama, keberagaman menjadi keniscayaan di Indonesia. Namun demikian masih banyak persolan yang melilit bangsa ini, terutama dalam hal kebebasan beragama. Beberapa pekan lalu lebih dari seribu orang berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, menuntut kebebasan beragama sekaligus menanggapi serangkaian peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama selama tahun 2010, termasuk pembubaran jemaat Kristen yang sedang menjalankan ibadah dan serangan terhadap jamaah Ahmadiyah. Pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pembela agama Islam. Pertanyaannya: kenapa reaksi masyarakat, termasuk lembaga-lembaga kekuasaan lemah jika dibanding dengan kelompok yang begitu kecil dan tidak berpengaruh tersebut?. Untuk menjawab masalah itu, kita harus melihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat pertama yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Namun pelaksanaan masih jauh panggang dari api. Kalu kita tengok ke belakang, kecenderungan itu menguat berkali lipat sesudah tahun 1965 dengan kemenangan salah satu kubu ideologis di Indonesia, kubu pro-kapitalisme anti-sosialis, pro-otoriterisme dan anti-kemerdekaan. Kekuasaan kediktatoran Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun itu bersandar pada kekuatan senjata untuk mempertahankannya. Selama periode Orde Baru kebijakan-kebijakan untuk mengkontrol pikiran orang semakin banyak. Sekolah tidak lagi dipakai untuk mendidik anak supaya kritis terhadap situasi di sekelilingnya. Cara berpikir kritis yang menjadi andalan semua pendiri bangsa – baik aliran Soekarno, maupun aliran Sjahrir maupun Hatta – dibuang ke tong sampah dan diganti dengan cara berpikir menghafal, mengiyakan dan menerima. Ini menegasi sepenuhnya hasil-hasil zaman pencerahan (Enlightenment atau Aufklarung) yang merubah wajah umat manusa di atas muka bumi. Aufklärung memang sesuatu yang berkembang di Eropa pada abad 18. Mungkin ada sebagian pendapat yang menyatakan ide aufklärung tidak relevan di Indonesia yang “mempunyai tradisi dan budaya sendiri”. Tapi pendapat itu salah. Karena salah satu sebab Indonesia bisa berdiri sebagai sebuah nasion baru juga dipengaruhi ide-ide aufklarung. Seluruh pendiri bangsa menganut ide-ide ini dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Sebenarnya gerakan-gerakan anti-kolonial di seluruh dunia pun merupakan salah satu perjuangan meneruskan nilai-nilai aufklärung. Salah satu definisi aufklärung seperti didedahkan oleh filsuf Immanuel Kant, “…. adalah kemunculan manusia dari ketidakdewasaan dirinya sendiri. Kant berpendapat bahwa ketidakmatangan terjadi bukan karena kurangnya pemahaman, namun akibat kurangnya keberanian untuk menggunakan salah satu gagasan, kecerdasan, dan kebijaksanaan tanpa bimbingan orang lain. Dengan kata lain seorang manusia takut untuk berpikir bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu Kant berseru bahwa moto pencerahan adalah “Sapere Aude!”. Beranilah menggunakan pengertian dan pengetahuan kamu sendiri! Itulah essensi dari pencerahan. Pada zaman kolonial rakyat Indonesia yang suka disebut “pribumi” oleh kekuasaan kolonial berpikir kalau dirinya harus terus-menerus mendapatkan bimbingan dari penguasa. Hal itulah yang ditolak oleh kaum intelektual pemberontak awal abad 20. Seiring tersebarnya kesadaran tersebut, jutaan rakyat jelata pun menolak berada di bawah ketiak kekuasaanmeneer-meneer penjajah. Dalam proses itu, kaum intelektual, baik mereka yang lulusan sekolah-sekolah formal ataupun matang di dalam organisasi pergerakan – menyerap dan mempelajari ide-ide pencerahan secara umum. Pembacaan terhadap karya-karya produk zaman aufklärung di Eropa menumbuhkan pengertian kritis terhadap dunia. Akumulasi ilmu pengetahuan menjadi pisau analisa sekaligus senjata utama untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri. Itu juga yang dilakukan oleh Sukarno di dalam memimpin gerakan pembebasan nasional di Indonesia. Sebagai pemikir paling berpengaruh, dia sering memperkenalkan ide-ide Rousseau dan Thomas Jefferson, dua pemikir besar zaman pencerahan, kepada rakyat Indonesia. Tetapi dengan pembasmian cara berpikir kritis sesudah tahun 1965, hilanglah juga sebuah cara berpikir memandang dunia (weltanschaung). Padahal itulah yang sebenarnya jadi senjata ampuh dalam perjuangan mendirikan Indonesia. Tanpa kebebasan untuk berpikir tentang semesta alamnya sendiri, rakyat digiring kepada bentuk gagasan produk pemikiran represif ciri khas rezim otoritarian: Tunduklah pada yang lebih tahu, yakni penguasa dan mereka yang mengaku sebagai ahli di bidang moralitas. Selama cara berpikir kritis yang dihidupkan oleh Kartini, Tirto Adhi Soerjo, Sukarno, Sjahrir, Hatta, Tan Malaka dan semua aktivis pembebasan nasional sebelum dan sesudah 1945 tidak dibangkitkan kembali, maka para manusia sok “pembimbing” akan selalu menguasai negeri ini. Membuat zaman kembali terkungkung dalam kegelapannya dan jauh dari ide-ide pencerahan yang dibawa oleh para aktivis itu. Jadi, beranilah berpikir dengan menggunakan pemikiranmu sendiri! Dan beranilah mengungkapkannya untuk kebaikan kita semua. Berjuanglah terus untuk merebut kembali zaman pencerahan yang telah Sukarno cs. bawa ke negeri ini. Dr. Max Lane adalah Indonesianis asal Australia. Ia penerjemah karya-karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer ke dalam bahasa Inggris. Mengajar di beberapa universitas di Melbourne, Australia. Ia penulis buku Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto(Verso, 2008). Kini tinggal di Melbourne dan seringkali di Tebet, Jakarta. |
|