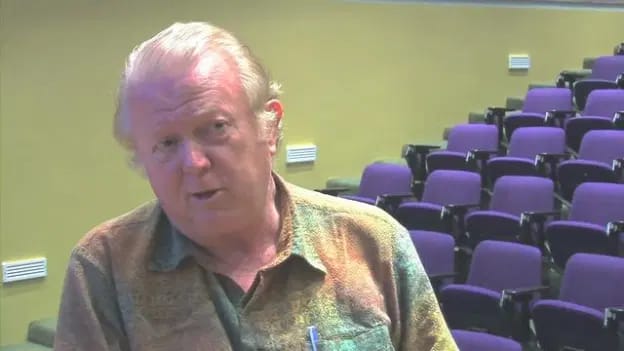Oleh: Coen Husein Pontoh, Max R. Lane
Di KALANGAN Indonesianis, yakni sarjana asing yang secara khusus mencurahkan kehidupan akademiknya untuk mempelajari Indonesia, posisi Max Lane adalah unik. Ia tidak hanya menggeluti aktivitas akademik, seperti riset, publikasi akademik atau seminar, tapi lebih dari itu terlibat aktif dalam pembangunan pergerakan progesif di Indonesia. Ia bukan hanya intelektual tapi juga seorang aktivis gerakan sosialis. Memparafrasekan Tesis XI Marx tentang Feuerbach, Max Lane tidak hanya sekadar menafsirkan tentang Indonesia, tapi ia juga ingin mengubahnya.
Hal lain yang unik dari lelaki yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris Tetralogi Buru karya sastrawan terbesar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, adalah optimismenya tentang masa depan gerakan kerakyatan di Indonesia. Memang semenjak jatuhnya rezim kediktatoran Soeharto, masa depan demokrasi tampak suram. Secara faktual, demokrasi kini telah dikuasai oleh para elite yang membentuk kartel politik, atau oligarki kapitalis yang berwatak predator. Dalam sistem demokrasi seperti itu, agenda-agenda kerakyatan akan selalu berakhir dengan kegagalan. Dan celakanya, kelompok-kelompok yang menyuarakan agenda kerakyatan ini kekuatannya sangat lah lemah sehingga tidak mampu mendesakkan atau bahkan memaksa para elite yang tergabung dalam kartel politik tersebut untuk memberikan respon yang serius. Terlebih lagi kalau kita berbicara tentang proyek politik sosialis, dengan serta-merta bermunculan sinisme, itu terlalu utopis.
Di hadapkan pada kesimpulan teoritik dan politik yang pesimistik itu, Max Lane justru melihat bahwa ada masa depan bagi gerakan progresif di Indonesia. Dan Indonesia, bagi Max Lane, hanya akan bergerak ke arah pemenuhan kebutuhan rakyatnya jika rakyat memiliki kekuasaan yang nyata. Tapi, apa alasan di balik kesimpulan itu? Bagaimana agar masa depan itu bisa direalisasikan? Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut petikan wawancara Coen Husain Pontoh dengan DR. Max R. Lane.

Sejak kapan Anda memiliki ketertarikan pada Indonesia?
Secara intelektual dan politik sejak tahun 1969, ketika saya menjadi mahasiswa Jurusan Indonesian and Malayan Studies, University of Sydney. Sebelumnya, tentu saja sebagai orang muda tinggal di Australia, kami semua mengerti bahwa Indonesia adalah negeri besar yang terdekat dengan Australia.
Bagian apa dari Indonesia yang paling menarik perhatian Anda dalam studi Indonesia?
Saya kira setiap negeri di dunia sama-sama menarik. Mungkin negeri yang besar dan sejarah peradabannya panjang, ada lebih banyak topik yang menarik. Tetapi apa saja yang dilakukan manusia, apalagi yang dilakukan bersama-sama dalam proses kemajuan, pasti menarik dari negeri manapun di dunia. Kebetulan saya menjadi terlibat dengan Indonesia, karena sempat ke sana ketika muda (berumur 17 tahun) dan memiliki persahabatan dan pengalaman yang kemudian berakumulasi menjadi ketertarikan lebih jauh. Pasti juga setiap aspek kehidupan bermasyarakat Indonesia, kalau dipandang dari sudut ‘kemenarikannya’ pasti, ya, menarik. Kalau dunia tidak memiliki masalah-masalah yang mengancam kemanusiaan, pasti banyak topik yang asyik.
Jadi buat saya semuanya sama-sama menarik.Tetapi pertanyaan Anda kan bukan mana yang menarik, tetapi mana yang menarik perhatian?
Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus ingat saya mendekatinya bukan sebagai ‘Indonesianis.’Sebagai Indonesianis – yaitu orang yang khusus mendalami Indonesia secara akademis – banyak yang menarik perhatian, karena menarik. Tetapi sejak awal, terutama karena saya adalah orang produk radikalisasi zaman 60an, dimana kala itu berilmu pengetahuan saja adalah percuma dan merupakan onani intelektual, kecuali ilmu tersebut dikembangkan dan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Di abad ke-20 dan sekarang abad ke-21, salah satu masalah kemanusiaan yang utama ialahunderdevelopment (keterbelakangan pembangunan ekonomi) yang merupakan warisan empat abad kolonialisme dan imperialisme. Tiga perempat penduduk dunia hidup dalam kemelaratan dan keterbelakangan karena ini. Bahkan keterbelakangan dan ketimpangan kekayaan ini justru semakin parah karena imperialisme masih berlanjut.
Sistem yang berlaku ini tidak waras. Memiskinkan milyaran manusia di seluruh dunia, sekaligus jaminan keadilan sosial di negeri imperialis sendiri tidak bisa direalisasikan. Ditambah lagi pemercepatan kerusakan alam sebagai habitat manusia makin tak terkendali.
Kita sebagai orang yang terlibat di dunia ilmu pengetahuan, baik di universitas maupun di luar universitas, harus bersikap bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus membantu penyelesaian masalah ini. Dan masalah ketimpangan hasil imperialisme ini adalah masalah ‘power,’ yaitu masalah politik dan perjuangan politik. Demokrasi, dalam arti kekuasan rakyat banyak (yaitu rakyat miskin), menjadi sebuah fokus perhatian dalam rangka mengakhiri ketimpangan struktural imperialis, kemelaratan dan keterbelakangan di bidang produktivitas, pendidikan dan kebudayaan.
Jadi, kalau kita kembali ke Indonesia, yang menarik perhatian saya ialah mempelajari proses-proses dimana rakyat miskin memperjuangkan kekuasaannya dalam situasi imbangan kekuatan politik antar kelas yang terus berubah, proses keterbelakangan di bidang ekonomi dan proses kebudayaan yang mencerminkan perubahan-perubahan di kesadaran kelas. Terlalu banyak memang.
Sebagai seorang Indonesianis, bagaimana Anda memposisikan diri di antara para Indonesianis lainnya selama ini?
Saya kira saya tidak sengaja atau dengan secara sengaja memposisikan diri saya di hadapan Indonesianis lain. Memang titik berangkatnya berbeda secara praktek. Pertama, saya ragu apakah istilah ‘Indonesianis’ sepenuhnya cocok buat saya, termasuk dalam hal kegiatan saya di universitas. Terbitan saya yang pertama dulu oleh sebuah universitas memang berkaitan dengan Indonesia, yakni terjemahan atas naskah drama Rendra, Kisah Perjuangan Suku Naga. Saya menulis esai untuk menganalisa naskah drama tersebut. Itupun saya menulisnya sesudah menjadi semacam anggota simpatisan Bengkel Teater selama satu tahun di Yogyakarta tanpa sebuah posisi resmi di universitas. Tetapi terbitan saya yang kedua justru tentang Filipina: The Urban Mass Movement in the Philippines (1990), terbitan Australia National University (ANU). Itupun hasil pengalaman dan riset dalam rangka terlibat di aktivitas solidaritas internasional dengan gerakan anti-kediktatoran Filipina di zaman Marcos, sekaligus dengan gerakan sosialis di Australia dan Filipina. Ketika ANU menerbitkan buku itupun, saya tidak berkedudukan di sebuah universitas, kecuali pernah sebagai Research Fellow di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) di Singapore selama 7 bulan. Selama di ISEAS itulah buku The Urban Mass Movement in the Philippines, saya tulis.
Singkatnya. selama ini saya selalu berinteraksi dengan universitas sebagai ‘orang luar.’ Sementara mayoritas orang yang dikenal sebagai Indonesianis sudah masuk dunia universitas sejak muda dan menjadikannya sebagai karir dan profesi.
Apa kritik Anda terhadap karya-karya para Indonesianis selama ini?
Wah, sebaiknya Anda menunggu buku saya yang akan terbit pada akhir tahun ini, dimana saya akan me-review semua karya para Indonesianis dari Herbert Feith sampai Ed Aspinall, Vedi Hadiz, Dan Slater dan Jeffrey Winters. Tetapi secara umum saya setuju dengan deskripsi Professor Aspinall dari ANU terhadap situasi studi politik Indonesia di Australia dewasa ini. Mungkin juga berlaku di Eropa, dan jelas berlaku untuk sebagian karya di Amerika Serikat. Dia menjelaskan tentang Indonesianis di Australia (termasuk dirinya) sebagai berikut: ‘[they have] an emphasis on elite dominance and recalcitrance being a widely accepted theme in studies of post-Suharto democratisation. If anything, they are distinguished chiefly by their pessimism about the prospects of Indonesia’s democratic transformation, a pessimism which derives from the absence in their analysis of the belief in revolutionary change and the transformative potential of subordinated groups that once animated left-wing scholarship.’ Yang disebut ‘pessimism’ yakni tentang potensi transformatif dari ‘subordinated groups’ (yaitu mayoritas manusia) yang sangat mempengaruhi agenda riset dan paradigma-paradigma analisanya. Salah satu cerminannya, misalnya, adalah ketidaktertarikannya pada masalah underdevelopment. Ada ketertarikan pada demokrasi tetapi bukan pada demokrasi (kekuasan rakyat banyak) sebagai alat untuk memperjuangkan struktur yang adil dan tanpa kemalaratan, tetapi sebagai suatu ‘fenomena’ tersendiri, atau terjebak di antara melihatnya sebagai fenomena tersendiri (democracy for democracy’s sake) dan berharap (tapi pesimis) akan membawa perubahan. Pendekatan ini berarti analisanya, pada akhirnya, mengandung banyak kesalahan dan kekeliruan. Tetapi ini topik besar. Sementara buku saya belum selesai, silahkan membaca Bab 7 dalam buku Sejarah Alternatif Indonesia terbitan Djaman Baroe, dimana saya sumbang satu bab tentang topik yang Anda tanyakan ini.
Sebagai penerjemah buku-buku Pramoedya Ananta Toer ke dalam bahasa Inggris, apa yang mendorong Anda untuk menerjemahkan karya-karya Pram?
Topik ini juga butuh beberapa buku untuk menjawabnya. Dan kebetulan ada buku saya, Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia, tentang karya-karya Pram, akan diterbitkan Djaman Baroe bulan Juni tahun ini. Tetapi secara lebih singkat: Bumi Manusia terbit awal tahun 80an. Langsung membaca buku ini – yang sebagai novel memang asyik dibaca – ‘Indonesia’ yang dikomunikasikannya berkebalikan 180 derajat dengan Indonesia yang dikomunikasikan oleh kekuasaan Orde Baru. KaryaBumi Manusia dan novel berikutnya menyampaikan sebuah cerita tentang kemandirian, kebudayaan melawan, keunggulan ilmu pengetahuan, kemunafikan kolonialisme Barat, dan analisa masyarakatnya sangat mendalam. Pada saat itu, saya menjadi percaya sekali bahwa buku ini harus dibaca di luar Indonesia, supaya orang bisa tahu Indonesia yang sebenarnya: Indonesia sebagai sebuah realitas yang sedang berproses mencari kemajuan peradaban. Realitas memang merupakan sebuah proses.
Apalagi, di luar Indonesia saat itu, citra Indonesia sangat jelek. Indonesia dilihat hanya melalui citra kekuasaan, yaitu militerisme Soeharto dengan korupsinya, penumpahan darahnya pada tahun 1965, Malari, Tanjung Priok, penembakan misterius, dan pendudukan Timor Leste. Citra ini memang mencerminkan kenyataan jadi harus diakui sebagai kenyataan. Tetapi ini tetaplah sebuah citra sehingga perlu dimunculkan cerita tentang Indonesia yang lain, yaitu yang melawan, dan bahwa Indonesia memang lahir sebagai anak kandung dari perlawanan atas ketidakadilan dan penindasan. Jadi, buku itu, menurut saya, harus segera terbit dalam bahasa Inggris. Pertimbangan pada waktu itu juga kenapaBumi Manusia harus secepatnya terbit di luar negeri, karena pertimbangan keamanan, yakni untuk melindungi pengarang dan penerbit di Indonesia sendiri. Keamanan mereka akan terbantu jika buku itu sudah dikenal dan diakui secara luas di dunia.
Dalam buku Unfinished Nation: Indonesia Before and After Soeharto, Anda banyak menjadikan karya-karya Pram sebagai sumber inspirasi teoritik. Bisa dijelaskan secara singkat apa inspirasi teoritik dari karya-karya Pram tersebut?
Ini juga saya jelaskan dalam buku Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia. Secara singkat, suatu hal yang kita bisa pelajari dari seri buku Bumi Manusia sampaiRumah Kaca ialah bahwa Indonesia merupakan sebuah mahkluk yang diciptakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Agen transformasinya adalah rakyat sendiri melalui gerakan organisasi massa – mulai dengan SDI-nya Tirto Adhisuryo dan diteruskan oleh anak ideologisnya pada zaman bergerak di tahun 20an – dipersenjatai oleh ide-ide anak semua bangsa. Berbeda dengan kaum liberal ‘kritis’ maupun kaum ‘political economist’ seperti professor Aspinall dkk., Pramoedya sama sekali tidak ‘pesimis’ tentang potensi transformatif kaum tertindas. (Sebenarnya konsep ‘pesimis’ itu sendiri tidak sepenuhnya ilmiah, suatu pertanda buruk ketika ilmuwan pakai istilah itu).
Jadi saya terinspirasi dengan konsep bahwa kemajuan-kemajuan manusia, termasuk juga pembebasan dari koloinialisme dan penciptaan negeri serta manusia baru, merupakan hasil daya kreatif massa sendiri. Carilah di sana untuk mengerti bagaimana pembebasan-pembebasan lain juga bisa tercapai!
Dalam buku tersebut, Anda juga memberikan tempat yang cukup penting bagi Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada dekade awal 1990an hingga jatuhnya rejim Orde Baru. Apa posisi penting atau apa sumbangan penting PRD pada masa itu?
Terutama PRD merupakan sebuah organisasi politik yang dengan serius, berkomitmen tetap, memiliki keberanian dan pandai secara intelektual serta sistematik dalam memperjuangkan kebangkitan gerakan anti-kediktatoran melalui aksi massa. Pada saat itu, strategi seperti itu adalah maha penting, meski sulit dan banyak risiko. Maha penting, karena, seperti yang saya berusaha jelaskan diUnfinished Nation, inti dari keseluruhan strategi politik Suharto dan Orde Baru ialah membasmi fenomena aksi massa dari muka bumi Indonesia. Politik aksi massa (dipersenjatai dengan ide-ide anak semua bangsa) hampir berhasil menjalankan revolusi sosial di Indonesia. Orde Baru berhasil membasmi aksi massa dari muka bumi Indonesia dan PRD justru menargetkan untuk menghidupkannya kembali, dan mereka berhasil. Kemudian, dengan sangat cepat, landasan kekuasaan Orde Baru hancur, jatuh. Perjuangan ini memakan korban di tangan kediktatoran. Ada 14 orang hilang, termasuk Wiji Thukul. Ada yang ditangkap. Ada yang disiksa-siksa. Ada yang dipukul-pukul.
Sebenarnya PRD bukan hanya itu – masih banyak yang seharusnya diungkap dan dijelaskan. Tetapi buat saya itulah yang paling penting kita tangkap dan memikirkannya pada waktu sekarang ini.
Setelah periode Soeharto, PRD seperti kehilangan relevansinya dan terpecah-pecah. Bagaimana Anda memberikan analisis terhadap kasus ini?
Iklan lagi: bulan April ini akan terbit kembali Bangsa Yang Belum Selesai dengan tiga bab baru yang membicarakan pertanyaan Anda itu. Sekarang saya bisa hitung delapan atau sembilan organisasi atau kelompok baru yang menggambarkan diri sosialis, atau kiri atau radikal. Mungkin ada lagi yang saya belum kenal. Belum lagi kalau kita masukkan penerbit kiri atau perorangan-perorangan. Secara jumlah, jelas kaum kiri sudah bertambah banyak sejak jatuhnya Suharto. Dalam abad 21 ini, dengan seluruh dunia ‘disatukan’ dalam sebuah sistem ekonomi global yang terstruktur secara imperialis, dan Indonesia baru terbebas pada periode 45 dari zaman politik gelap, jelas akan melahirkan banyak kelompok dan aliran. Mengapa? Karena memang tidak akan langsung jelas sekali apa persisnya yang harus dilakukan ke depan. Akan membutuhkan akumulasi pengalamam maupun akumulasi pekerjaan intelektual dalam hal analisa, termasuk debat tertulis (polemik). Semua itu sedang berlangsung dan semoga akan semakin cepat berkembang. Proses pencarian jalan baru ini, di sebuah periode baru pasca Suharto, juga dihadapi oleh teman-teman anggota PRD. Pada 1998, PRD secara riil hanya sempat mengakumulasi pengalaman kurang dari 10 tahun. Mayoritas anggotanya bahkan lebih sedikit lagi. PRD menjadi bagian dari proses umum yang berkembang di Indonesia dalam hal proses pencarian jalan baru dan pengelompokkan yang berkembang sebagai perwujudan pencarian-pencarian ini. Orang yang pernah punya pengalaman di PRD bisa ditemukan di pimpinan PRP, KPO-PRP, PPR dan sekarang PR, dan di sekitar Rumah Buruh (Bekasi). Juga masih ada PRD itu sendiri dengan penerbitannya Berdikari Online, meski buat saya tidak jelas apa itu masih berhaluan kiri atau sudah nasionalis centrist. Belum lagi yang aktif di LSM, penerbitan dan jurnalistik. Saya kira akselerasi pencarian jalan yang tepat pada saat sekarang ini dipicu oleh beberapa perubahan penting dalam politik konflik kelas di Indonesia. Biasanya hal itu tercermin pada perpecahan-perpecahan dan penggabungan-penggabungan; semoga disertai dengan debat tertulis supaya rakyat juga bisa ikut dalam prosesnya secara maksimal.
Dalam periode sekarang ini, kita lihat ada begitu banyak perlawanan terhadap rejim kapitalisme-neoliberal tetapi belum ada satu organisasi perjuangan kelas yang kuat dengan basis massa yang terorganisir. Apa pendapat Anda soal ini?
Ada perlawanan, tetapi belum terlalu banyak mengingat jumlah penduduk Indonesia (230 juta) dan penderitaan yang dihadapi. Ini biasa dan wajar. Terlalu banyak orang tangisi ini, seolah-olah ini kesalahan gerakan atau mencerminkan kegagalan gerakan kiri. (Kalau tak ada kehidupan ideologis tertulis itu mungkin suatu kegagalan sementara.) Pada tahun 1965, kebiasaan dan tradisi membangun gerakan organisasi massa dalam rangka rakyat kecil memperjuangakan nasibnya dibasmi total dengan memakai teror terbesar sesudah Perang Dunia kedua. Bahkan memori terhadap tradisi tersebut juga dibasmi total. Hanya sedikit sekali memori yang tersisa, itupun terdengar samar-sama,seperti kata-kata seputar ‘Sukarno’ dan ‘rakyat’ – dan itupun tidak jelas. Itu berlangsung selama 33 tahun di bawah kediktatoran yang berusaha keras untuk mempertahankan situasi ini. Selama 10 tahun (1998-2008), kekuasaan negara bukan hanya tetap di tangan kelas sosial yang sama tetapi banyak orangnya juga masih sama. Maklumlah, belum ada organisasi perjuangan kelas tertindas yang kuat. Sangat bisa diduga.
Dan dalam situasi kekosongan total yang sangat riil ini – artinya yang berlangsung selama 40 tahun – organisasi massa seperti itu hanya mungkin diluncurkan kembali oleh kekuatan sosial masyarakat dan bukan oleh ‘kekuatan aktivis’ kiri. Akan membutuhkan social weight, yaitu yang meluncurkannya harus memang mewakili satu bagian dari masyarakat yang terdiri dari jumlah orang yang banyak dan berposisi strategis pada saatnya dan juga memiliki sumber daya materiil. Usaha-usaha meluncurkan partai massa (biarpun kecil) seperti Popor, kemudian Papernas, atau partai buruhnya Mokhtar Pakpahan semua dicoba sebelum faktor kekuatan yang memiliki social weight, posisi strategis dan resources, ada.
Dalam tiga tahun terakhir ini, dengan berkembangnya gerakan serikat buruh sektor formal yang melahirkan MBPI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) dan yang mampu melakukan mogok nasional, situasi sudah berubah. Ini dirasakan oleh semua orang, termasuk serikat buruh kecil yang berhaluan ideologis terbuka dan lebih kiri. Saya kira dinamika yang sedang berkembang ini, asal tidak direpresi atau dikhianati, sedang menciptakan situasi untuk melahirkan sebuah gerakan politik rakyat buruh ataupun sebuah partai buruh. Saya tidak bisa ramalkan mekanismenya. Apalagi diluncurkan oleh semua atau sebagian serikat buruh melalui pengurusnya atau strukturnya? Atau melalui mekanisme di luar itu? Atau kombinasi? Atau melalui perpecahan ataupun gabungan? Siapa tahu. Yang penting: alangkah baiknya kalau ada usaha serius untuk membangun persatuan seluas-luasnya dan sesolid-solidnya dari semua serikat buruh dan serikat tani dalam rangka memperjuangan perbaikan kesejahteraan rakyat. Fokus persatuan yang luas sekarang sangat dimungkinkan ke gerakan serikat buruh. Sementara, dengan sadar bahwa sebuah gerakan serikat buruh (ataupun sebuah partai buruh yang terlahirkan oleh gerakan tersebut) tak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ketimpangan struktural. Akan butuh juga akselerasi pencarian strategi dan kemampuan menjelaskannya pada rakyat oleh kalangan calon kader radikal.