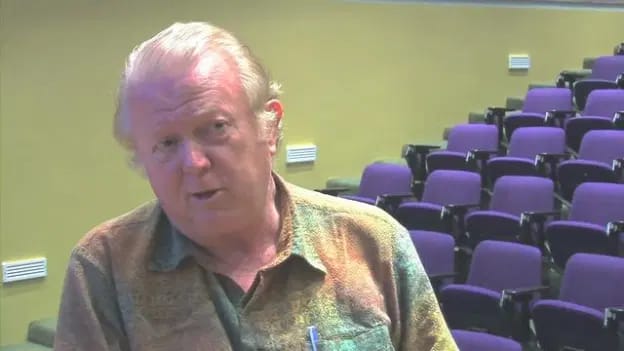Barbara Ehrenreich**
Artikel yang pertama kali muncul dalam majalah WIN tanggal 3 Juni, 1976, dan dicetak kembali di sini atas izin pengarang, merupakan pemikiran klasik sosialis feminis. Setelah puluhan tahun perdebatan atas isu-isu ini, kebutuhannya, dalam pandangan kami, tidak pernah berkurang.—Editor
Pada tingkatan tertentu, mungkin tak terlalu pas dijabarkan, feminisme sosialis telah ada sejak lama. Kau adalah perempuan di dalam masyarakat kapitalis. Kau dilanda amarah: menyangkut pekerjaan, tagihan-tagihan, suamimu (atau mantan), sekolah anak-anak, pekerjaan rumah, cantik atau tak cantik, diperhatikan atau tak diperhatikan (dan juga tak didengar), dll. Jika kau memikirkan semua ini dan bagaimana semua itu cocok satu sama lain, serta apa yang harus diubah, kemudian kau mencari kata-kata yang sekaligus menyiratkan semua pikiran ini dalam bentuk singkat, kau akan hampir mendapatkan apa yang disebut “feminisme sosialis.”
Banyak diantara kita menjadi feminisme sosialis hanya dari cara semacam itu. Kita sedang mencari sebuah kata/istilah/frasa untuk mulai mengekspresikan semua keresahan kita, semua prinsip kita, dengan cara yang sepertinya bukan “sosialis” maupun “feminis”. Aku harus akui bahwa banyak kaum feminis sosialis yang aku kenal juga tak senang dengan istilah “feminis sosialis”. Di satu sisi (istilah) itu terlalu panjang (aku tak berharap pada suatu sambungan pergerakan massa); di sisi lain nama itu juga masih terlalu pendek untuk apa yang disebut feminisme sosialis internasionalis antirasis dan anti heteroseksis.
Persoalan ketika memberi label baru pada sesuatu adalah ia serta merta menciptakan aura sektarianisme. “Feminisme sosialis” menjadi suatu tantangan, suatu misteri, suatu bahasan dalam dan pada dirinya sendiri. Kita memiliki para pembicara, konferensi-konferensi, artikel-artikel mengenai “feminisme sosialis”—meskipun kita tahu persis bahwa baik “sosialisme” dan “feminisme” terlalu besar dan terlalu umum sebagai bahan yang bagus untuk setiap pidato, konferensi, artikel, dll. Orang, termasuk yang menyatakan diri sebagai feminis sosialis, bertanya pada diri mereka sendiri, “Apa itu feminisme sosialis?” Ada semacam ekspektasi bahwa ia adalah (atau akan demikian dalam beberapa saat, mungkin dalam pidato, konferensi atau artikel berikutnya) sintesis yang brilian dari bagian-bagian historis dunia—suatu lompatan evolusioner Marx, Freud, dan Wollstonecraft. Atau ia akan berubah menjadi tiada arti, suatu model yang digunakan oleh segelintir feminis dan sosialis feminis yang resah, suatu gangguan sementara saja.
Aku mau mencoba menerobos beberapa misteri yang telah tumbuh disekitar feminisme sosialis. Suatu cara logis memulainya adalah dengan melihat sosialisme dan feminisme secara terpisah. Bagaimana seorang sosialis, lebih tepatnya, seorang Marxis, melihat dunia? Bagaimana seorang feminis? Untuk memulainya, Marxisme dan Feminisme memiliki memiliki satu kesamaan penting: keduanya adalah cara pandang kritis dalam melihat dunia. Keduanya menghancurkan mitologi rakyat dan kebiasaan “awam” dan memaksa kita untuk melihat pengalaman dengan suatu cara baru. Keduanya mencoba memahami dunia—bukan dalam bentuk keseimbangan statis, simetris, dll (seperti dalam ilmu sosial konvensional)—namun dalam bentuk yang antagonisme. Keduanya menuju kesimpulan yang menggelegar dan menggelisahkan dan, disaat bersamaan, juga membebaskan. Tak akan bisa memiliki cara pandang Marxis atau feminis dan tetap sekadar menjadi seorang penonton. Untuk memahami realitas yang dijentrengkan oleh analisa ini, artinya bergerak menjadi aksi untuk mengubahnya.
Marxisme mengarahkan dirinya pada dinamika kelas dalam masyarakat kapitalis. Setiap ilmuwan sosial tahu bahwa masyarakat kapitalis ditandai oleh, lebih kurang, ketidaksetaraan yang sistemik. Marxisme mengerti ketidaksetaraan ini muncul dari proses yang melekat pada kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi. Minoritas orang (kelas kapitalis) memiliki seluruh pabrik-pabrik/sumber-sumber energi/sumber-sumber daya, dll, yang membuat mayoritas orang lain bergantung padanya untuk dapat bertahan hidup. Mayoritas (kelas pekerja) harus memenuhi semua kebutuhan, di bawah kondisi yang diciptakan oleh kapitalis, sesuai upah yang dibayar kapitalis. Karena kapitalis menghasilkan keuntungan dengan membayar upah lebih rendah daripada nilai sebenarnya yang diciptakan oleh pekerja, hubungan antara dua kelas ini tak terhindarkan menjadi salah satu antagonisme yang tak terdamaikan. Kelas kapitalis bergantung hidup pada kesinambungan eksploitasi atas kelas pekerja. Apa yang mempertahankan sistem kekuasaan kelas ini, pada akhirnya, (adalah) kekerasan. Kelas kapitalis mengontrol (secara langsung maupun tak langsung) alat-alat kekerasan terorganisir dalam wujud negara—polisi, penjara, dll. Hanya dengan mengobarkan perjuangan revolusioner yang bertujuan mengambil alih kekuasaan negara maka kelas pekerja dapat membebaskan dirinya, dan pada akhirnya, semua orang.
Feminisme mengarahkan dirinya pada ketidaksetaraan yang lazim lainnya. Seluruh masyarakat manusia ditandai oleh sekian derajat ketidaksetaraan antar jenis kelamin. Jika kita sekilas mengamati masyarakat manusia, disepanjang sejarah dan di berbagai benua, kita lihat bahwa mereka sama-sama dicirikan oleh: penundukan perempuan di bawah otoritas laki-laki, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat secara umum; pemberhalaan perempuan sebagai sebuah properti; pembagian kerja seksual dimana perempuan dibatasi pada aktivitas seperti pemeliharaan anak, merawat orang tua laki-laki, dan bentuk-bentuk khusus kerja produktif (biasanya bereputasi rendah).
Kaum feminis, diserang oleh kelaziman yang hampir-hampir universal dari semua itu, telah mencari suatu penjelasan dari ‘takdir’ biologis yang terdapat di sepanjang kehidupan sosial manusia. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan rata-rata, khususnya dibandingkan perempuan hamil atau perempuan yang menyusui bayi. Lebih jauh lagi, laki-laki memiliki kekuasaan untuk membuat perempuan hamil. Oleh karena itu bentuk-bentuk ketidaksetaraan seksual terletak—meski beragam bentuknya dari satu budaya ke budaya lain–, akhirnya, pada apa yang dengan jelas berupa kelebihan fisik yang laki-laki miliki atas perempuan. Yang artinya, akhirnya, terletak pada kekerasan, atau pada ancaman kekerasan.
Akar biologis dan paling awal dari supremasi laki-laki—sebenarnya kekerasan laki-laki—biasanya dikaburkan oleh hukum-hukum dan konvensi yang mengatur hubungan antar jenis kelamin dalam budaya tertentu di manapun. Namun, penindasan itu ada menurut analisis feminis. Kemungkinan serangan/pelecehan laki-laki terjadi sebagai suatu peringatan terus menerus terhadap perempuan yang “nakal/jahat” (melawan, agresif), dan membuat perempuan “baik” menjadi bertanggung jawab ke dalam supremasi laki-laki. Penghargaan karena telah menjadi “baik” (“cantik”, “patuh”) adalah (mendapat) perlindungan dari berbagai kekerasan laki-laki dan, dalam beberapa kasus, jaminan ekonomi.
Marxisme menghancurkan mitos mengenai “demokrasi” dan “pluralisme”nya dengan menunjukkan suatu sistem kekuasaan kelas yang bersandarkan pada pemaksaan eksploitasi. Feminisme menghancurkan mitos mengenai “insting” dan cinta romantis untuk menunjukkan aturan laki-laki sebagai aturan kuasa. Kedua analisa menghendaki kita melihat pada ketidakadilan yang mendasar. Pilihannya adalah memenuhi kehendak mitos-mitos tersebut, atau seperti Marx menyebutnya, memperjuangkan tata kehidupan sosial yang tidak membutuhkan mitos-mitos untuk mempertahankannya.
Adalah mungkin untuk menjumlahkan Marxisme dan feminisme dan hasilnya “feminisme sosialis.” Sebetulnya, mungkin, inilah cara pandang yang kerap digunakan oleh banyak kaum feminis sosialis–semacam hibrida, mendorong feminisme kita ke dalam lingkaran sosialis, sosialisme kita ke lingkaran feminis. Namun, satu persoalan ketika meninggalkannya demikian, adalah, membuat orang tetap bertanya-tanya “Baiklah, tapi apa sebenarnya itu?” atau menuntut pada kita “Apa kontradiksi pokoknya.” Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, yang kedengarannya memaksa dan otoriter, seringkali menghentikan kita dalam perjalanan: “Buatlah pilihan!” “Satu atau yang lainnya!” Namun kita tahu bahwa terdapat suatu konsistensi politis terhadap feminisme sosialis. Kita bukanlah hibrida atau netral tak bersikap.
Untuk menuju pada konsistensi politis tersebut kita harus membedakan diri kita, sebagai feminis, dari feminis yang lain, dan sebagai Marxis, dari Marxis lainnya. Kita harus mengawasi (maaf atas terminologinya) feminisme jenis feminis sosialis dan sosialisme jenis sosialis feminis. Hanya dengan begitu terdapat satu kemungkinan hal-hal akan “berarti” lebih dari (sekadar) suatu penyajaran (pensejajaran) yang problematik.
Kupikir banyak kaum feminis radikal dan feminis sosialis akan setuju pada kapsul karakterisasi ku terhadap feminisme sejauh ini. Masalahnya dengan kaum feminisme radikal, dari sudut pandang feminis sosialis adalah, ia tak akan menuju ke mana-mana. Ia tetap terpaku pada universalitas supremasi laki-laki—hal yang tak pernah benar-benar berubah; semua sistem sosial yakni patriarki; imperialisme, militerisme, dan kapitalisme adalah semata-mata ekspresi dari agresifitas bawaan laki-laki. Dan lain-lain.
Masalahnya dengan ini, dari sudut pandang sosialis feminis, adalah bukan saja tak menyertakan laki-laki (dan kemungkinan rekonsiliasi dengan mereka atas landasan yang benar-benar setara dan kemanusiaan) namun juga meninggalkan banyak hal buruk tentang perempuan. Contohnya, mendistorsi negeri sosialis seperti China sebagai “patriarki”— saya dengar kaum feminis radikal mengatakannya—adalah mengabaikan perjuangan nyata dan capaian jutaan perempuan. Feminis sosialis, sambil bersetuju bahwa terdapat hal yang universal dan tanpa batas waktu menyangkut penindasan perempuan, telah menegaskan bahwa hal itu memiliki berbagai bentuk berbeda dalam seting berbeda-beda, dan perbedaan itu adalah sangat penting. Terdapat perbedaan antara suatu masyarakat dimana seksisme diekspresikan dalam bentuk pembunuhan bayi perempuan, dan suatu masyarakat dimana seksisme mengambil bentuk perwakilan tak setara di dalam Komite Sentral. Dan perbedaan tersebut pantas diperjuangkan hidup dan mati.
Salah satu variasi historis menyangkut seksisme, yang harus diperhatikan seluruh kaum feminis, adalah seperangkat perubahan yang muncul bersama dengan transisi dari suatu masyarakat agraris ke masyarakat industri kapitalisme. Ini bukanlah isu akademik. Sistem sosial yang digantikan kapitalisme industrial pada dasarnya adalah sistem sosial patriarkis, dan aku menggunakan istilah ini sekarang dalam makna aslinya, untuk mengartikan suatu sistem dimana produksi dipusatkan dalam rumah tangga dan dipimpin oleh laki-laki tertua. Kenyataannya adalah bahwa kapitalisme industrial hadir dan merobek sistem tersebut dari bawah patriarki. Produksi dibawa ke pabrik-pabrik dan individu ditarik dari keluarga untuk menjadi pekerja upahan “bebas”. Mengatakan bahwa kapitalisme mengacaukan organisasi produksi patriarkal dan kehidupan keluarga, bukan, tentu saja, mengatakan bahwa kapitalisme menghapuskan supremasi laki-laki! Namun benar bahwa bentuk-bentuk tertentu dari penindasan jenis kelamin yang kita alami saat ini, hingga derajat yang signifikan, adalah perkembangan yang baru. Suatu diskontinuitas historis terbentang antara kita dan patriarki yang sebenarnya. Jika kita hendak memahami pengalaman kita sebagai perempuan hari ini, kita harus bergerak pada suatu pemikiran mengenai kapitalisme sebagai suatu sistem.
Pasti terdapat cara lain agar aku dapat sampai pada poin yang semacam ini. Aku dapat saja sekedar bilang bahwa, sebagai feminis, kita paling banyak tertarik pada perempuan yang paling tertindas—perempuan miskin dan kelas pekerja, perempuan di dunia ketiga, dll—dan atas alasan ini kita mengarah pada kebutuhan untuk memahami dan mengkonfrontasi kapitalisme. Aku dapat saja bilang bahwa kita butuh menekankan sistem kelas karena kita adalah anggota kelas. Namun aku mencoba menunjukkan hal lain mengenai perspektif kita sebagai feminis: bahwa tak mungkin kita mengerti seksisme sebagai suatu tindakan atas hidup kita, tanpa meletakkannya ke dalam konteks historis kapitalisme.
Kupikir, sejauh ini, mayoritas feminis sosialis juga akan setuju dengan kemasan kapsul teori Marxis. Dan masalahnya lagi-lagi adalah bahwa banyak sekali orang (aku menyebutnya ”Marxis mekanik”) yang tidak beranjak ke mana-mana. Kepada orang-orang ini, satu-satunya yang “nyata” dan penting yang terjadi dalam masyarakat kapitalis adalah hal-hal yang terkait proses produktif atau lapangan politik konvensional. Dari sudut pandang tersebut, setiap bagian lain pengalaman dan keberadaan sosial—hal-hal yang terkait pendidikan, seksualitas, rekreasi, keluarga, seni, musik, kerja rumah tangga (sebutkan saja)—merupakan pinggiran dari dinamika utama perubahan sosial; hal tersebut adalah bagian dari “superstruktur” atau “kebudayaan”.
Feminis sosialis berada pada kubu yang sangat berbeda dari apa yang aku sebut “Marxis mekanik.” Kita (bersama dengan banyak, banyak Marxis lainnya yang tidak feminis) melihat kapitalisme sebagai suatu totalitas sosial dan kebudayaan. Kita memahami bahwa dalam kepentingannya mencari pasar, kapitalisme berkehendak memasuki setiap pojok dan celah kehidupan sosial. Khususnya pada fase kapitalisme monopoli, lapangan konsumsi sekecil apapun sama penting, dari sudut pandang ekonomi saja, seperti halnya dalam lapangan produksi. Sehingga kita tidak bisa memahami perjuangan kelas sebagai sesuatu yang terbatas pada isu upah dan jam kerja, atau sebatas isu-isu tempat kerja. Perjuangan kelas terjadi dalam setiap arena dimana kepentingan-kepentingan kelas berkonflik, dan itu termasuk pendidikan, kesehatan, seni, music, dll. Kita bertujuan untuk mentransformasi tak hanya kepemilikan alat-alat produksi, melainkan totalias kehidupan sosial.
Sebagai Marxis, kita mendekati feminisme dari tempat yang benar-benar berbeda ketimbang Marxis mekanik. Karena kita melihat kapitalisme monopoli sebagai sebuah totalitas politik, ekonomi, dan kebudayaan, kita memiliki ruang di dalam bingkai Marxis terhadap isu-isu feminisme yang tak berhubungan jelas dengan produksi atau “politik”, isu-isu yang memiliki hubungan dengan keluarga, layanan kesehatan, dan kehidupan “pribadi”.
Lebih jauh lagi, di dalam jenis Marxisme kita, tidak ada “persoalan perempuan”, karena sejak awal kita tidak pernah mengkompartementalisasi perempuan keluar dari “superstruktur” atau (diletakkan) di tempat lain. Marxis dengan kecenderungan mekanik terus menerus mendengungkan isu perempuan tak berupah (ibu rumah tangga): apakah ia anggota kelas pekerja? Tepatnya, apakah ia benar-benar memproduksi nilai lebih? Kita bilang, tentu saja ibu-ibu rumah tangga adalah anggota kelas pekerja—bukan karena kita memiliki bukti jelas apakah mereka benar-benar memproduksi nilai lebih—namun karena kita mengerti, bahwa kelas terdiri dari orang-orang, dan memiliki suatu kehidupan sosial yang jauh (berbeda) dari areal produksi yang didominasi kapitalis. Ketika kita memikirkan kelas dengan cara ini, lalu kita lihat bahwa pada dasarnya perempuan yang tampak paling terpinggir, ibu-ibu rumah tangga, berada (justru) pada jantung kelasnya—membesarkan anak, menyatukan keluarga, memelihara jaringan kultural dan sosial komunitas.
Kita menjadi satu jenis feminisme dan satu jenis Marxisme yang kepeduliannya beriring berjalan secara cukup natural. Kupikir sekarang kita sampai pada posisi untuk melihat mengapa feminisme sosialis telah begitu dimistifikasi: gagasan feminisme sosialis merupakan misteri besar atau paradoks, sepanjang yang dimaksud sosialisme adalah yang aku sebut “Marxisme mekanik” dan apa yang dimaksud dengan feminisme adalah suatu jenis feminisme radikal yang ahistoris. Kedua hal ini tak bisa sekadar dihubung-hubungkan; mereka tak sama.
Namun jika kau rekatkan bersama sosialisme jenis lain dan feminisme jenis lain, seperti yang aku coba definisikan, kau akan dapat beberapa landasan yang sama dan itu adalah salah satu yang terpenting mengenai feminisme sosialis saat ini. Ia adalah ruang—bebas dari penciutan atas feminisme yang dipendekkan dan versi Marxisme yang dipendekkan—dimana kita dapat mengembangkan jenis politik yang mengurusi totalitas politik/ekonomi/kebudayaan dari masyarakat kapitalis monopoli. Kita hanya dapat menuju ke sana, sejauh ini, melalui jenis feminisme yang sudah ada, jenis Marxisme konvensional, dan lalu kita harus memutus untuk menjadi sesuatu yang tidak terlalu terbatas dan tak lengkap dalam pandangannya tentang dunia. Kita harus mengambil nama baru, “feminisme sosialis”, bertujuan untuk menyatakan kehendak kita menyatukan keseluruhan pengalaman kita dan membangun suatu politik yang merefleksikan totalitas dari kesatuan tersebut.
Namun demikian, aku tidak mau meninggalkan teori feminisme sosialis sebagai suatu “ruang” atau landasan bersama. Hal-hal memang mula-mula berkembang dalam “landasan” tersebut. Kita menjadi lebih dekat pada suatu sistesis dalam pemahaman kita mengenai seks dan kelas, kapitalisme dan dominasi laki-laki, dibandingkan beberapa tahun lalu. Di sini aku akan mengindikasikan, hanya dengan sekilas-ringkas, menyangkut garis pemikiran tersebut:
- Pemahaman Marxis/feminis bahwa dominasi kelas dan seks bersandarkan, akhirnya, pada kekerasan adalah benar, dan ini tetap menjadi kritik paling jahat terhadap masyarakat kapitalis/seksis. Namun terdapat banyak hal terkait pernyataan “akhirnya” tersebut. Dalam hal kesehariaan, banyak orang rela pada dominasi kelas dan seks tanpa dibariskan oleh ancaman kekerasan, dan seringkali bahkan tanpa ancaman kekurangan material.
- Maka sangat penting kemudian, untuk mencari tahu apa itu, jika bukan penggunaan kekerasan secara langsung, dalam menjalankan segala sesuatu. Menyangkut kelas, sudah banyak yang menulis tentang kenapa kelas pekerja AS kurang memiliki kesadaran kelas yang militan. Tentu saja pembagian etnik, khususnya pemisahan hitam/putih, merupakan bagian kunci jawabannya. Namun aku berpendapat, selain dibuat pemisahan, kelas pekerja secara sosial sudah diatomisasi (dipisah-pisah). Lingkungan kelas pekerja telah dihancurkan dan dibuat rusak; hidup telah diprivatisasi sedemikian rupa dan mementingkan diri sendiri; keterampilan yang dahulu dimiliki kelas pekerja telah diambil alih oleh kelas kapitalis; dan “kebudayaan massa” yang dikontrol kapitalis menyisihkan hampir semua institusi dan kebudayaan asli kelas pekerja. Bukannya kolektifitas dan kemandirian sebagai sebuah kelas, (namun justru) terdapat saling isolasi dan ketergantungan kolektif pada kelas kapitalis.
- Penundukan perempuan, yang dikarakterisasi oleh masyarakat kapitalis tahap lanjut, merupakan kunci dari proses atomisasi kelas ini. Atau dengan kata lain, kekuatan-kekuatan yang telah mengatomisasi kehidupan kelas pekerja dan mempromosikan ketergantungan material/kebudayaan pada kelas kapitalis adalah kekuatan yang sama yang bertanggung jawab terhadap penundukan perempuan. Perempuan lah yang paling terisolasi dalam keberadaan keluarga yang telah semakin terprivatisasi (bahkan juga ketika mereka bekerja di luar rumah). Itulah, dalam banyak contoh, keterampilan perempuan (keterampilan produksi, pengobatan, kebidanan, dll), yang telah diragukan bahkan dilarang demi melapangkan jalan bagi komiditas. Perempuanlah, pertama-tama, yang didorong menjadi benar-benar pasif/tidak kritis/bergantung (dengan kata lain “feminin”) berhadapan dengan sebaran penetrasi kapitalis ke dalam kehidupan pribadi. Secara historis, penetrasi kapitalis tahap lanjut pada kehidupan kelas pekerja telah memilih perempuan sebagai target utama pasifikasi/”feminisasi”—karena perempuan adalah para pemegang-kebudayaan kelas mereka.
- Selanjutnya terdapat interkoneksi mendasar antara perjuangan perempuan dengan apa yang secara tradisional dipahami sebagai perjuangan kelas. Tidak semua perjuangan perempuan secara inheren memiliki desakan antikapitalis (khususnya bukan mereka yang hanya menghendaki kekuasaan dan kekayaan bagi kelompok perempuan tertentu), namun, semua yang membangun kolektivitas dan kemandirian kolektif di kalangan perempuan, sangat penting untuk pembangunan kesadaran kelas. Selain itu, tidak semua perjuangan kelas secara inheren memiliki desakan antiseksis (khususnya bukan mereka yang menggandol nilai-nilai patriarkal praindustri), namun, semua yang berkehendak membangun otonomi sosial dan kebudayaan kelas pekerja, sangat berkaitan dengan perjuangan pembebasan perempuan.
Ini merupakan, dalam garis besar yang sangat kasar, satu arah yang diambil oleh analisis feminis sosialis. Tak ada yang mengharapkan suatu sintesa muncul yang akan menjatuhkan perjuangan feminis dan sosialis menjadi hal yang sama. Kapsul rangkuman yang aku berikan sebelumnya mengandung kebenaran “akhir”: bahwa terdapat aspek-aspek penting dari dominasi kapitalis (seperti penindasan rasial) yang perspektif feminis murni tidak dapat mengaitkan atau mengatasinya—tanpa distorsi yang aneh. Terdapat aspek-aspek penting dari penindasan seks (seperti kekerasan laki-laki di dalam keluarga) yang sangat sedikit ada dalam pemikiran sosialis—lagi, tanpa distorsi dan banyak pengaretan. Oleh karena itu butuh untuk terus menjadi sosialis dan feminis. Namun, terdapat cukup sistesis, baik dalam apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan, untuk mulai percaya diri memiliki identitas sebagai feminis sosialis.
*http://www.marxists.org/subject/women/authors/ehrenreich-barbara/socialist-feminism.htm
** Barbara Ehrenreich adalah pengarang 13 buku termasuk Bait and Switch: The (Futile) Pursuit of the American Dream, yang akan datang dari Metropolitan Books, dan Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America (Metropolitan Books, 2001).
–Diterjemahkan oleh Zely Ariane