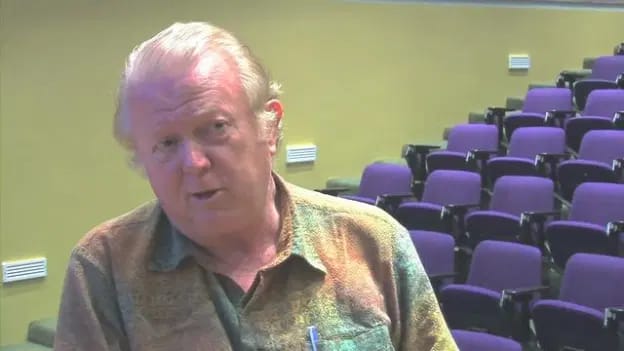Ganjar Krisdiyan
Ganjar Krisdiyan
Dalam rapat konsultasi di DPR pada Senin (3/10/2011), bersama pimpinan KPK, Kepala Polri, Jaksa Agung, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi, politisi PKS, Fachri Hamzah (Wakil Ketua Komisi III) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengeluarkan pernyataan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan KPK adalah lembaga superbody (sangat berkuasa), sehingga tidak ada yang mampu mengontrol, menurutnya badan superbody tidak boleh ada didalam negara demokrasi. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pendapat politisi Partai Demokrat, Benny K Harman, (Ketua Komisi III) DPR, yang merasa bahwa KPK sebagai teroris bagi anggota DPR. Menyusul setelahnya, dalam kesempatan yang berbeda, giliran Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, meskipun lebih moderat, bahwa KPK perlu di evaluasi. Jauh sebelumnya, Ketua DPR, yang juga berasal dari Partai Demokrat, Marzuki Alie, memberikan pernyataan yang sama, tentang pembubaran KPK, karena beberapa pimpinan dan staff KPK diperiksa oleh badan etik KPK dalam kasus Nazaruddin.
Entah apa maksud dari pernyataan para politisi tersebut, jika mereka memang berkehendak menumpas korupsi di Indonesia, benarkah jalan keluar yang ditawarkan dengan pembubaran KPK? Yang mereka anggap kewenangannya terlalu luas, efektifitasnya masih minim, menebar teror kepada pejabat publik sehingga menurunkan kinerja dll, atau, seperti yang banyak dinilai oleh para pengamat, bahwa pernyataan anggota DPR tersebut adalah semacam ancaman kepada KPK untuk melindungi diri dari kejahatannya, karena belakangan, KPK telah memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Mencari jalan keluar untuk mencegah tindakan korupsi, memang menjadi problem tersendiri bagi bangsa Indonesia, sejak Orde Lama hingga memasuki Orde Reformasi ini, berbagai kebijakan dan lembaga dibentuk, namun pemberantasan kasus-kasus korupsi masih gagal. Dalam sejarah, kegagalan pemberantasan korupsi lebih banyak disebabkan oleh perlawanan dari elit yang merasa terancam dengan keberadaan lembaga pemberantasan korupsi.
Pada masa Orde Lama di Kabinet Djuanda, Dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda. Yang kedua, pada tahun 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir dengan kegagalan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Menurut Bohari (2001), bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.
Masa Orde Baru, Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.
Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.
Pada masa Reformasi, Di era reformasi, B.J. Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.
Tetapi, nasib KPK saat inipun sedang diujung tanduk, seperti yang dijelaskan diawal, selain pernyataan-pernyataan yang diucapkan para politisi DPR yang berkehendak membubarkan KPK, saat ini DPR juga sedang menggodok perubahan UU tentang KPK, yang rencananya akan menghapus salah satu kewenangan pokok KPK yaitu kewenangan untuk melakukan tuntutan. Apabila kewenangan ini dicabut dan mengembalikan kewenangan penuntutan kepada Kejaksaan dan Polri, hal tersebut tentu saja sama dengan membubarkan KPK, pemberantasan korupsi cukup mengandalkan polisi dan jaksa. Menurut Abdullah Hehamahua, penasihat KPK, efektivitas KPK dalam memberantas korupsi justru terletak pada penyatuan antara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada satu organisasi.
Nasib tragis, dari upaya pemberantasan korupsi dari periode ke periode menunjukan bahwa, masih kuatnya rezim korup di Indonesia, elit politik dengan kekuasaan ditangannya, dengan mudah mengambil uang rakyat tanpa hambatan yang berarti, korupsi merajalela masuk ditulang sumsum kekuasaan sehingga menjadi mustahil mengharapkan pemberantasan korupsi dapat diatasi oleh elit-elit politik, apa yang dilakukan DPR terhadap KPK misalnya, adalah upaya kolektif untuk saling melindungi antar pejabat yang terlibat kasus-kasus korupsi setelah KPK mencium bau busuk dalam Bangar DPR.
Dari sinilah kontrol rakyat harus dijalankan, mengharapkan pemberantasan korupsi ditangan elit sama saja menjauhkan panggang dari api, karena hampir bisa dipastikan mayoritas (jika tidak bisa dikatakan semua) elit negeri ini tidak bersih dari tindakan korupsi. Rakyat harus mampu mengawasi jalannya pemerintahan, dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan dalam mengkampanyekan isu-isu rakyat, dan membentuk wadah-wadah seluas-luasnya, dan melibatkan diri dalam upaya memberantas korupsi. Terhadap ancaman pembubaran KPK, rakyat harus bersikap memberi dukungan yang kritis terhadap KPK. Yang dimaksud dengan dukungan kritis adalah, bahwa seburuk apapun wajah KPK sekarang, dia masih menguntungkan bagi upaya pemberantasan korupsi, namun, kelemahan utama KPK adalah, dia tidak berbasis partisipasi rakyat, sehingga membuat efektivitasnya rendah, mudah dibubarkan, bahkan membuka celah bagi penyelewengan internalnya, oleh sebab itu, rakyat harus mendorong agar lembaga KPK ini menjadi lebih partisipatif dan dapat dikontrol langsung, dan mendorong pembentukannya hingga ke daerah-daerah, agar kasus-kasus korupsi lebih banyak tertangani.***
Referensi-referensi:
- INILAH.COM; Senin, 1 Agustus 2011
- INILAH.COM; Selasa, 4 Oktober 2011
- KOMPAS.COM; Selasa, 4 Oktober 2011
- REPUBLIKA.CO.ID; Rabu, 05 Oktober 2011
- http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi Pemberantasan Korupsi.
- INILAH.COM; Kamis, 13 Oktober 2011.