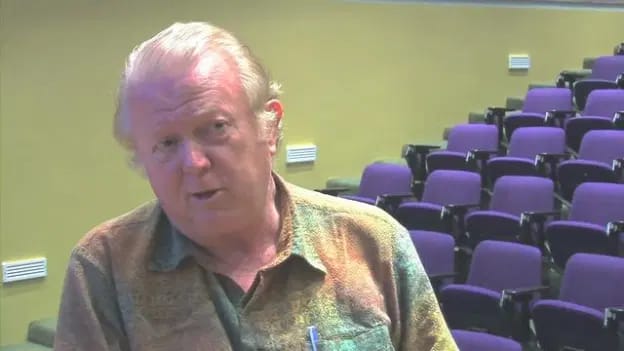Edwin Erlangga*
Perkenalan saya dengan Tiziano Terzani, terus terang terjadi secara kebetulan. Barangkali sebuah kebetulan yang membawa kemujuran. Bagi saya pribadi melalui tulisan – tulisannya saya mendapatkan banyak sekali “pencerahan”, setidaknya dalam memahami dunia dan peradaban dari perspektif komparatif.
Baiklah, bermula pada tahun 2006, saat pertama kali saya masih mengeja rangkaian kata dalam bahasa ibu nya, bahasa italia. Di sebuah perpustakaan kota, saya menemukan sebuah buku dengan judul yang langsung menarik perhatian saya ” In Asia”. Ketika itu saya sedang giat – giatnya mencari pemahaman akan basis ” dialog peradaban”. Sebuah pertemuan yang barangkali “ditakdirkan” begitu saya seringkali berujar pada diri sendiri, dengan tanpa maksud melebih – lebihkan.
Pembaca tentu penasaran siapakah sesungguhnya Tiziano Terzani ?, baiklah akan saya terangkan agar pembaca menjadi jelas akan sosoknya.
Tiziano terzani, seorang ” fiorentino” dilahirkan di sebuah propinsi yang terkenal dengan tradisi “rinascimento” yang sangat kuat. Menempuh pendidikan di kota Firenze dari keluarga yang tidak terlalu mampu secara ekonomi. Dalam sebuah wawancara Terzani diminta untuk memaparkan masa kecilnya, dan pengalaman yang paling membekas dalam benaknya adalah ketika Terzani kecil harus menggunakan sepatu yang sama untuk berbagai aktivitas sekolah. Ya, Italia ketika itu jauh dari kondisi yang kita kenal saat ini, Italia ditahun 40 an masih sedang berjuang untuk keluar dari perang besar yang melanda eropa. Sempat bergabung dan menjadi kader ” penuh waktu” Partai Komunis Italia (PCI). Namun setelah keputusan Komintern untuk menginvasi Hungaria, Terzani serta merta menanggalkan keanggotaanya dan memutuskan untuk mencari “kebenaran lain diluar partai”, sebuah istilah yang sangat lazim bagi seorang marxist yang kecewa terhadap kebijakan Partai.
Pada pertengahan tahun 60 an, Eropa ketika itu sedang dilanda “demam revolusi” yang dipimpin oleh kaum muda pasca perang. Pertumbuhan ekonomi melesat tajam, terjadi pertarungan nilai yang cukup tajam di masyarakat terutama antara generasi tua dengan generasi muda yang secara politik lebih progresif dan berani secara etik-moral untuk memperjuangkan nilai – nilai zaman. Mengutip seorang filsuf Jerman Herder yang kemudian direkonstruksi kembali oleh Hegel, maka kaum muda eropa ketika itu terhirup aroma “Zeitgeist” atau semangat zaman, dan memacu diri sebagai generasi untuk berjuang dalam pertarungan nilai.
Puncak periode tersebut secara politik dapatlah kita sebut peristiwa ” Paris 1968″. Suatu peristiwa sosial yang kemudian mencapai titik kulminasi politiknya dengan “penyingkiran” Jenderal Charles de Gaulle selama “revolusi” yang berlangsung beberapa pekan. Namun persitiwa tersebut kemudian menjalar bagai air bah keseluruh eropa menuntut; liberalisasi dan demokratisasi sistem pendidikan tinggi, pematangan gagasan sosial progresif seperti ide feminisme, kesetaraan sosial. Namun tusukan yang paling dalam menghujam jantung nilai-nilai “peradaban tua” adalah penentangan terhadap kolonialisme/imperialisme yang lebih banyak berisi penegasan terhadap perang di Asia, Indo-China.
Di kampus – kampus yang menjadi motor pergerakan ini seperti di Universitè de Sorbonne atauUniversitè de Nanterre, simbol – simbol pahlawan perang ketika Perancis diduduki fasis di Vichy digantikan oleh sosok – sosok pejuang pembebasan nasional seperti Mao Tse Tung atau Ho Chi Min. “Timur” ketika itu itu menjadi sumber inspirasi anak – anak muda eropa yang muak dan jenuh terhadap pertentangan nilai di dalam sistem kapitalistik itu sendiri. Anak – anak muda itu mencari sumber penghidupan filosofis alternatifnya. Dalam kontruksi itu mereka menemukan “Asia” atau “Timur” sebagai obat dari dekadensi jamannya.
Maka setelah peristiwa tersebut mencapai puncak kematangan ideologis dan politiknya. Terjadilah“migrasi intelektual” ke arah “Timur”. Sebagai contoh, kita tentu ingat bagaimana George Harrison, pergi meninggalkan “the beatles” ketika terjadi vacum panjang dan memutuskan untuk mempelajari instrumen sitar di India. Banyak sekali “generasi bunga“ ini yang juga kemudian sampai di Indonesia, salah satunya seorang seniman atau Indonesianis Jean Coteau yang kemudian mendalami kebudayaan Nusantara di Bali.
Tiziano Terzani
Dalam konteks itu Tiziano Terzani adalah salah seorang eropa yang juga terbius oleh semangat jaman yang juga mencari sumber – sumber kebenaran lain yang saat itu Eropa dilihatnya sebagai “zaman dekadensi”.
Setelah menyelesaikan studi bahasa China di Columbia University, Terzani memutuskan untuk bergabung dengan surat kabar jerman “Der Spiegel” dan menjadi koresponden tetap wilayah Asia Tenggara dengan pos tugas di Singapura pada tahun 1971. Selain memantau China dan secara khusus meliput perang yang tengah berlangsung di Indochina, Terzani juga sedikit banyak memantau perkembangan yang terjadi di Indonesia, terutama di Timor ditengah “kegelapan” informasi yang menyelimuti wilayah Indonesia pada umumnya. Tiziano Terzani termasuk salah satu jurnalis asing yang berhasil memantau perkembangan sosial-politik yang terjadi di Timor pra-integrasi (atau aneksasi) dengan Indonesia, sebagai akibat dari desakan kaum muda Portugis yang menuntut dekolonialisasi sebagai bagian atau dampak dari revolusi bunga atau “carnation revolution” di Portugal.
Dalam catatan jurnalistiknya yang kemudian dibukukan dengan judul ” Pelle di Leopard” (1973) Terzani dengan lantang mengecam keras perang Indochina yang ketika itu tengah berlangsung. Dalam film dokumenter yang dibuat oleh James Petras, secara terbuka Petras memuji hasil karya jurnalistik para “jurnalis-kombaten” di garis depan ini, tanpa mereka tak akan mungkin kampanye anti-perang dapat berhasil memobilisasi jutaan kaum muda yang tumpah ruah di jalan – jalan kota besar di Eropa maupun di Amerika. Dan secara terbuka pula, Komandan Tertinggi Angkatan Perang Amerika menyatakan kegagalan perang Indochina selain persoalan taktik perang juga karena kampanye massif hasil jurnalis anti-perang yang merusak mental prajurit di garis depan. Yah, untuk pertama kalinya dalam perang modern, jurnalisme memainkan peran yang signifikan dalam kancah pertempuran yang sesungguhnya.
Saya masih ingat kalimatnya sangat reflektif terhadap kenyataan perang, Terzani menulis “la guerra è una cosa triste, ma la cosa più triste è che ci fa abitudine”. Ya, perang adalah hal yang menyedihkan, namun hal yang jauh menyedihkan adalah ketika kita terbiasa akan perang. Kalimat itu menghujam ulu hati saya, dihempaskannya kesadaran saya hingga limbung dibuatnya, harga diri dan kehormatan saya digugat sedemikian kerasnya justru setelah saya mendapati bahwa ketika saya menulis artikel ini disebuah tempat yang aman dan nyaman, di belahan dunia yang lain perang – perang kecil dengan intensitas yang sangat masif tengah berlangsung; di Amerika, Eropa, Afrika dan Asia.
Bagi saya pribadi refleksi Tiziano Terzani sedemikian dalam terhadap observasinya terhadap Asia. Banyak refleksi atau perenungan tersebut ditulis dalam karya jurnalistik, yang sepintas mengingatkan saya terhadap bentuk – bentuk catatan etnografis karya penulis eropa antara abad ke 16 – 18. Apabila saat ini mulai berkembang tradisi penulisan jurnalistik yang dikenal sebagai “peace jurnalism”, maka model penulisan Terzani perlu ditelaah sebagai model.
Catatan pada “In Asia”
Terbit pada tahun 1998 oleh penerbit Longanesi, sebuah karya jurnalistik yang menjadi “jembatan” pada pemahaman holistik untuk mendorong “dialog Timur – Barat”.
Baiklah sebelum kita berbicara lebih lanjut, rasanya perlu kita membongkar terlebih dahulu terminologi yang bagi saya secara pribadi cukup menganggu. Terminologi tersebut adalah “Timur” dan “Barat”. Baiklah, apa yang salah dengan terminologi tersebut, dan apa pula keberatan saya? Tanpa panjang lebar saya akan mencoba membongkar persoalan tersebut. Semoga acara ” bongkar membongkar” ini memiliki faedah nya; sebuah pemahaman dasar bagi “dialog peradaban”.
“Timur” dan “Barat” sebagai terminologi dalam penulisan sejarah seringali mengacu pada periodisasi ketika terjadi pembelahan dalam Imperium Romawi pada tahun 285 Masehi oleh Kaisar “Diocleaziano” sebagai solusi terhadap upaya reorganisasi administratif kekuasaan Imperium yang semakin luas dan juga untuk menangani kesulitan mengontrol wilayah yang sedemikian luas dari pemberontakan sipil di dalam maupun serangan – serangan bangsa barbarian dari luar (barbarian – adjektif: mengacu pada hal apa pun yang bukan romawi, sering mengacu pada konotasi tidak beradab).
Imperium “Romawi Barat” yang terakhir dipimpin oleh Kaisar “Teodosio” berakhir pada abad ke 4 setelah ibukota nya Ravenna yang diserang habis – habisan pasukan barbar. Imperium “Romawi Timur” atau Imperium Byzantinum yang berada di Konstantinopoli, Turki saat ini, tegak berdiri hingga abad ke 14 dan menjadi saksi peralihan zaman baru.
Dalam penulisan sejarah, abad pertengahan eropa selesai ketika Colombus mendarat di pantai selatan benua Amerika. Dengan pendaratan itu, maka selesai lah abad pertengahan eropa, yang juga menandai berakhirnya signifikansi Konstantinopoli sebagai sebuah kekuasaan Imperial (dagang) ketika itu.
Menarik untuk dicatat bahwa, terminologi “Timur” dan “Barat” ini juga kemudian mengacu pada model corak produksi yang dikembangkan kedua “entitas” kebudayaan ini. Para sarjana abad ke 18 – 19 mencoba menganalisa hubungan ini dalam kerangka “relasi produksi” dimana “Timur” menjadi penyokong utama kemajuan pra-industrial di “Barat”, atau dalam terminologi kekinian berfungsi sebagai “penyuplai bahan – bahan mentah”.
Barangkali ada baiknya saya paparkan sedikit bagaimana hubungan tersebut tidak sekaku seperti yang dibayangkan oleh para sarjana konservatif.
Pada abad ke 8 – 9 di Eropa, terjadi perang besar yang berlangsung secara intensif dan cukup lama hingga menghabiskan hampir separuh populasi. Buruk dan parahnya kondisi tersebut diperkuat dengan ditemukannya praktek kanibalisme sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari gentingnya wabah kelaparan. Ketika itu Di Eropa kelaparan dan penyakit merajalela. Pertanian hancur dan bibit penyakit, terutama infeksi mewabah. Namun dalam jangka waktu yang relatif singkat, hanya dua ratus tahun, populasi dan kondisi hidup masyarakat Eropa berangsur membaik. Pada abad ke 10 sudah mulai ditemukan alat – alat mekanis guna menunjang intensifikasi pertanian.
Penyelamatan datang dari “Timur”. Ya, saat itu Konstantinopoli sudah menjadi pusat perdagangan barang – barang dari “Timur Jauh”, telah datang “barang ajaib” yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, barang itu; Merica!
Sejarawan bersama ahli nutrisi berkesimpulan, konsumsi merica ditenggarai sebagai penyelamat kemerosotan demografis eropa ketika itu. Dengan merica, penyakit infeksi dapat disembuhkan, menyelamatkan jutaan populasi dari tuberkolosis atau penyakit dingin yang melanda eropa ketika itu. Namun lebih jauh, penemuan fungsi merica sebagai alat konservasi makanan merupakan inovasi yang menyelamatkan populasi sehingga bahan pangan dapat disimpan ketika stok sedang berlebih. Kemampuan melakukan konservasi makanan ini dan mengatur surplus bahan pangan, mendorong lompatan – lompatan kebudayaan yang kemudian berlanjut pada mekanisasi atau inovasi teknologi.
Apabila pembaca mengenal jenis daging kering yang dikenal sebagai “ham” atau “prosciutto”, sangat sederhana sekali cara pengawetannya. Cukup melumurkan merica hitam kering segar pada bagian daging yang basah bersama garam, lalu disimpan di gudang – gudang bawah tanah yang kering. Reaksi kedua senyawa tersebut menghasilkan model pengawetan daging yang gurih, kering dan nikmat. Ketika terjadi krisis stok pangan segar, daging – daging kering yang telah diawetkan ini menjadi penyelamat. Apabila manusia modern mengenal kulkas, maka manusia abad pertengahan mengenal merica sebagai medium konservasi makanan.
Maka ketika kemampuan teknologi dan navigasi telah berkembang, maka dimulailah zaman baru. Zaman pelayaran mencari negeri – negeri asing yang kaya, liar dan misterius. Pramoedya Ananta Toer mengatakan sebagai “zaman perburuan rempah”. Dalam “Arus Balik” Pramoedya Ananta Toer, kedatangan bangsa – bangsa utara di Nusantara tiba pada saat yang tidak menguntungkan bagi Nusantara. Karena kekuatan armada laut Imperium Majapahit sendiri telah hancur luluh lantah akibat perang internal yang tidak jelas juntrungannya. Mataram menyerang basis kekuatan laut, yang secara militer tidak jelas keuntungannya bagi basis pertahanan militer Rakyat Nusantara. Sehingga mudahlah kekuasaan Raja – Raja Nusantara di pecah belah. Kalau hipotesa ini dapat dibenarkan, kalau saja ketika armada pasukan Nusantara berhasil mengkonsolidasi diri dengan kerajaan – kerajaan lokal lainnya merebut kembali pelabuhan dagang Malaka, maka tentu Rakyat Nusantara memiliki sejarah kejayaan nya yang lain. Bangsa Nusantara kalah di satu pertempuran yang sangat signifikan hingga berdampak pada 400 tahun kemerosotan. Namun perlu juga dicatat bahwa dalam setiap pertempuran, armada laut yang dipimpin oleh “Marsekal” Pati Unus telah dengan gagah berani mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Bangsa Nusantara dalam penyerbuan Malaka. Walaupun gagal, Bangsa Nusantara telah kalah terhormat dengan melawan.
Secara lebih struktural dan ideologis, kekalahan tersebut dicoba untuk di internalisasi. Yah, “Timur” sebagai pecundang yang kalah dan “Barat” sebagai pemenang. Walaupun telah terjadi proses dekolonialisasi, yang artinya kemerdekaan secara politik. Namun sesungguhnya secara akademis, wilayah “new emerging forces” menggunakan istilah Soekarno, tidak serta merta terbebas. Perlu pertarungan dan pergulatan pula di wilayah akademis.
Saya akan menunjuk pada karya Edward Said yang berjudul “Orientalism”. Sebuah karya ilmiah yang mengangkat popularitas nya setinggi langit. Dalam studi kesusastraan “post-colonialism” dapat kita temukan segudang catatan kaki yang merujuk pada Edward Said, ketika “Timur” atau “Oriental” yang dicoba untuk direkonstruksi.
Pangkal penolakan saya bersumber dari ketika kita berbicara “Timur” atau “Barat” kita sesungguhnya sedang masuk dalam perspektif keilmuan yang sangat “Eurosentris”. Saya menggugat dialog “Timur” dan “Barat” dalam posisi yang tidak seimbang, sejajar. Maka cukup beralasan ketika saya selalu menggunakan tanda petik ketika saya menulis “Timur” dan “Barat”.
Dari catatan Tiziano Terzani saya mendapatkan kebijaksanaan atau setidaknya upaya untuk memahami Asia sebagai lingkup geografis atau “Timur” dalam konteks identitas budaya dan sejarahnya. Setidaknya bagi saya pribadi upaya itu terlihat luar biasa untuk dapat memahami akar atau persoalan – persoalan fundamental yang terjadi di “Timur”.
Pada tahun 1971, ketika mendapatkan tugas pertama untuk memantau kawasan Asia, terlihat bahwa Terzani bukan saja memiliki pemahaman yang baik atas latar belakang ekonomi-politik kawasan, namun memiliki nalar filosofis yang baik untuk mencari akar persoalan konflik dari perspektif filosofis, kebudayaan.
Menjadi masuk akal menempatkan landasan dialog antar kebudayaan dalam perspektif yang sempat pula ditawarkan oleh Presiden Obama dalam Diskursus antar Peradaban di Universitas Al – Azhar, Mesir dua tahun yang lalu. Kemudian diskursus tersebut di lanjut di Balairung Universitas Indonesia, setahun yang lalu. Dari dua diskursus tersebut kita bisa mengafirmasi dan mengambil model dialog bahwa persoalan “Timur” dan “Barat” sesungguhnya persoalan kasat yang juga perlu dikonstruksi ulang. Karena sesungguhnya sejarah peradaban dunia menunjukan bahwa terjadi interaksi di antara dua “entitas” kebudayaan tersebut.
Saya pribadi juga menolak hipotesa Samuel Hungtington dalam “clash of civilization” yang mengajukan bahwa persoalan “identitas kebudayaan” menjadi poros konflik dalam pertarungan paska “perang dingin”.
Apabila interaksi antar kebudayaan yang secara historis merupakan fakta sejarah, sesungguhnya kita sedang membagi ruang bersama, termasuk identitas kebudayaan. Maka menjadi absurd ketika pertarungan dibangun diatas basis yang idealistik. Musuh bersama peradaban dunia justru berada pada kumampuan manusia untuk mengatasi tantangan kondisi sejarahnya; Kemiskinan, Perubahan Iklim yang mengancam bencana kelaparan di tahun – tahun mendatang. Kita perlu melompati fase sejarah dari konflik antar Bangsa menjadi resolusi persoalan antar Bangsa.
Mengutip pernyataan Tiziano Terzani dalam “Lettere Contro la Guerra” (Surat Menolak Peperangan), “Solo se riusciremo a vedere l’universo come un tutt’uno in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, comincieremo a capire chi siamo e dove stiamo”. Yah, Hanya jika kita dapat melihat dunia sebagai sebuah kesatuan dimana setiap hal mencerminkan totalitas dan keindahan yang terbesar adalah dalam setiap perbedaan, maka kita dapat mulai melihat dan memahami siapa kita dan dimana kita saat ini.
Maka sebagai penutup saya akan sampaikan dan tegaskan bahwa “BHINEKA TUNGGAL IKA” adalah benar, sebagai “kendaraan” berfikir untuk mencapai pemahaman holistik akan keberadaan manusia di dunia.
*Mahasiswa program studi Kesusastraan Modern Italia di Università degli Studi Bologna. Pemimpi paruh waktu, pembaca penuh waktu. ” a profesional dreamer, qualified risk taker”.